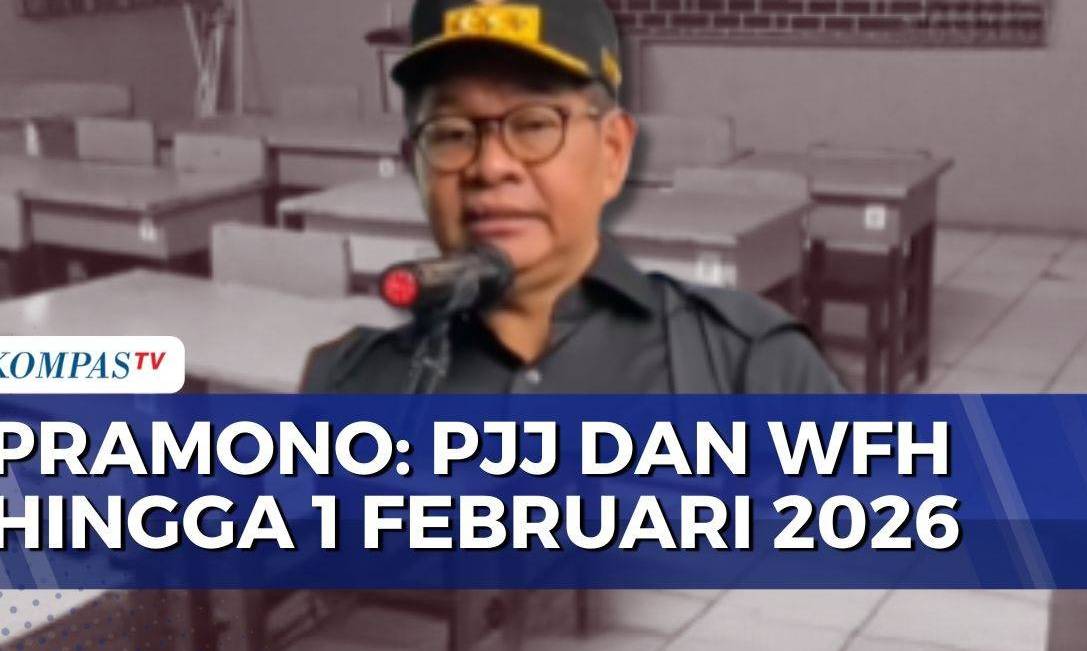Di tengah derasnya arus pemberitaan yang silih berganti—tentang politik, ekonomi, hingga sensasi media sosial—sebuah keputusan penting Mahkamah Konstitusi justru berlalu nyaris tanpa sorotan memadai. Tak banyak media arus utama memberi ruang serius bagi Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025.
Padahal, bagi wartawan dan masa depan kebebasan pers di Indonesia, keputusan ini adalah kabar yang sangat berharga. Ironisnya, perlindungan hukum bagi kerja jurnalistik—yang seharusnya dirayakan sebagai kemajuan demokrasi—malah tenggelam di tengah badai post-media: ketika logika klik, algoritma, dan viralitas lebih menentukan perhatian publik ketimbang bobot substantif sebuah putusan hukum.
Putusan yang dibacakan pada 19 Januari 2026 tersebut menegaskan prinsip fundamental negara hukum. Wartawan tidak dapat langsung dituntut pidana maupun digugat perdata hanya karena menjalankan tugas jurnalistiknya.
Mahkamah Konstitusi menafsirkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara kontekstual dan sistemik. Mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penyelesaian melalui Dewan Pers harus ditempatkan sebagai pintu utama sebelum jalur pidana atau perdata ditempuh. Dengan konstruksi ini, MK membentangkan payung konstitusi—memberi perlindungan dari kriminalisasi, sekaligus menjaga pers tetap bekerja dalam koridor etik dan tanggung jawab.
Tak Semua Kasus Pers adalah PembungkamanBagi wartawan yang sehari-hari bekerja di lapangan, putusan ini ibarat payung yang dibentangkan negara di tengah cuaca demokrasi yang kerap berubah. Ia tidak menghentikan hujan, apalagi badai, tetapi memberi ruang aman agar kerja jurnalistik berjalan dengan baik.
Namun, sebagaimana payung, perlindungan konstitusional tidak menghapus kewajiban untuk berhati-hati. Kebebasan pers bukan sekadar soal dilindungi dari ancaman hukum, melainkan juga kesediaan memikul tanggung jawab profesional atas setiap kata yang dipublikasikan.
Meski demikian, realitas lapangan menunjukkan bahwa payung konstitusi belum sepenuhnya membuat wartawan aman. Laporan Tahunan LBH Pers 2024 mencatat setidaknya 112 pengaduan terkait kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Pada periode yang sama, terdokumentasi 67 peristiwa kekerasan terhadap pers dengan 96 korban—mulai dari intimidasi, pelaporan pidana, gugatan perdata, perusakan alat kerja, hingga kekerasan fisik saat liputan. Data ini menunjukkan bahwa badai yang dihadapi wartawan bukan hanya datang dari negara atau aparat, tetapi juga dari aktor non-negara dan iklim sosial yang makin permisif terhadap pembungkaman.
Namun, tidak semua sengketa pers adalah pembungkaman. Di sinilah pentingnya membedakan kritik jurnalistik yang lahir dari kepentingan publik dengan pemberitaan yang melanggar prinsip etik. Pengalaman Dewan Pers menunjukkan bahwa dalam sejumlah kasus besar, persoalan justru diselesaikan melalui mekanisme etik, bukan pidana.
Kasus Tempo tahun 2010 tentang “rekening gendut” perwira Polri menjadi preseden penting: isu kepentingan publik tetap harus diuji melalui verifikasi, keberimbangan, dan ketepatan data. Dua belas tahun kemudian, pada 2025, pengaduan Kementerian Pertahanan terhadap Tempo terkait rencana darurat militer juga diselesaikan melalui jalur Dewan Pers.
Meski begitu, mekanisme etik ini tidak lepas dari kritik. Banyak pihak mengeluhkan bahwa pemulihan reputasi sering kali tidak sebanding dengan dampak pemberitaan awal. Tulisan yang dianggap merugikan reputasi muncul besar, menonjol, dan cepat menyebar, sementara klarifikasi hadir singkat, terlambat, dan tak jarang hanya berupa surat pembaca. Dalam konteks ini, payung konstitusi memang terbentang, tetapi badai opini publik sudah terlanjur mengamuk.
Paradoks Pers di Masyarakat ModernFenomena ini dapat dibaca melalui perspektif teori sistem Niklas Luhmann. Dalam The Reality of the Mass Media (2000), Luhmann menjelaskan paradoks masyarakat modern: kita mengenal dunia melalui media massa, sekaligus meragukan kebenarannya. Informasi yang telah dipublikasikan—benar atau salah—tetap berfungsi sebagai realitas sosial. Media bekerja sebagai sistem autopoietik yang menyeleksi realitas melalui pembedaan informasi dan noninformasi.
Pandangan ini dipertegas oleh Hermin Indah Wahyuni dalam Komunikasi Autopoiesis: Sebuah Pengantar Memahami Perspektif Sistem Niklas Luhmann (2025). Ia menjelaskan bahwa media massa tidak sekadar menyampaikan fakta, melainkan mengonstruksi realitas sosial dengan menentukan apa yang dianggap penting dan apa yang dikesampingkan. Dalam masyarakat modern, informasi media menjadi titik awal pengetahuan bersama, sehingga komunikasi sosial dapat berlangsung. Dengan logika ini, apa yang luput dari sorotan media berisiko hilang dari kesadaran publik—termasuk putusan MK yang sejatinya krusial bagi perlindungan pers.
Transformasi ini kian kompleks dalam konteks yang oleh Lev Manovich disebut sebagai era post-media. Dalam The Language of New Media (2001), Manovich menunjukkan bahwa media kontemporer telah digerakkan oleh perangkat lunak, algoritma, dan ekonomi perhatian. Nilai sebuah peristiwa tidak lagi terutama ditentukan oleh signifikansi sosialnya, melainkan oleh kesesuaiannya dengan ritme digital: cepat, emosional, dan mudah diperdagangkan sebagai atensi.
Di sinilah kritik Ben-Hur Haig Bagdikian dalam The New Media Monopoly (2004) menjadi sangat relevan. Bagdikian mengingatkan bahwa konsentrasi kepemilikan media dan logika industri informasi membuat ruang publik tidak pernah benar-benar netral. Media cenderung menyeleksi isu berdasarkan kepentingan ekonomi dan struktur kekuasaan, bukan semata kepentingan publik. Apa yang diberitakan berulang kali akan tampak penting, sementara yang jarang diangkat akan menghilang dari kesadaran kolektif.
Dalam struktur semacam ini, putusan Mahkamah Konstitusi yang melindungi wartawan justru berisiko mengalami marginalisasi simbolik: sah secara konstitusional, tetapi lemah secara diskursif. Payung konstitusi memang terbentang, namun di tengah badai post-media yang digerakkan oleh kepentingan pasar dan algoritma, perlindungan itu tidak selalu hadir sebagai kesadaran publik.
Sertifikasi Wartawan Jadi Kunci PentingKarena itu, penguatan profesionalisme menjadi kunci. Peran Dewan Pers perlu diperkuat, tidak hanya sebagai penengah sengketa, tetapi juga penjaga mutu profesi. Uji kompetensi dan sertifikasi wartawan harus dipandang sebagai fondasi etis, bukan sekadar formalitas administratif. Wartawan yang kompeten memahami kapan kritik dibutuhkan, bagaimana verifikasi dilakukan, dan di mana batas antara kepentingan publik dan sensasi.
Pers kerap disebut sebagai pilar demokrasi. Namun pilar hanya bermakna jika dirawat dan dilindungi. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menyediakan payung konstitusi. Tantangannya kini adalah memastikan payung itu benar-benar digunakan untuk berteduh—bukan ditinggalkan di tengah badai post-media yang makin kencang. Optimisme terhadap masa depan pers Indonesia tetap layak dipelihara, selama kebebasan berjalan seiring tanggung jawab, dan media bersedia kembali menempatkan substansi di atas sensasi. Di situlah martabat jurnalisme menemukan maknanya sebagai tugas mulia dalam republik yang demokratis.