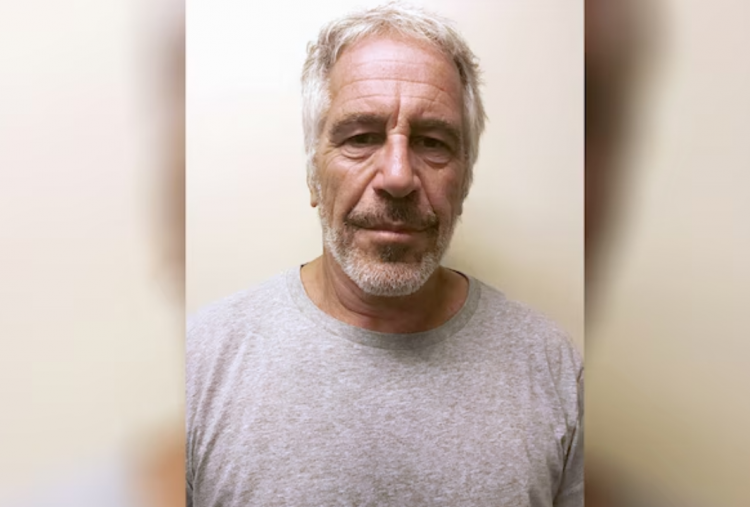Sejak pandemi COVID-19, pendidikan di Indonesia mengalami pergeseran besar menuju pembelajaran berbasis digital. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan bahwa sekitar 45,3 juta pelajar menjalani pembelajaran jarak jauh melalui sistem daring. Lebih dari 4.000 perguruan tinggi dengan sekitar 7 juta mahasiswa dan ratusan ribu dosen beralih ke kelas daring.
Transformasi pendidikan pada skala nasional ini menjadikan kursus, webinar, dan pelatihan daring sebagai salah satu ruang pembelajaran yang dapat dijalani pelajar dan mahasiswa sampai kini. Namun, kemudahan tersebut kerap menggeser orientasi belajar, dimana sertifikat dari hasil webinar dan pelatihan lebih diprioritaskan daripada pemahaman dan penguasaan materi. Kondisi ini mencerminkan krisis makna pendidikan, ketika proses belajar direduksi menjadi urusan administratif, bukan pembentukan kompetensi dan karakter.
Fenomena ini perlahan membentuk budaya belajar yang dangkal di kalangan pelajar dan mahasiswa. Beberapa studi mencatat bahwa selain motivasi untuk belajar, sertifikat dianggap sebagai salah satu alasan signifikan peserta webinar mendaftar. Sehingga wajar jika dalam praktiknya tidak sedikit pelajar dan mahasiswa yang mengejar sertifikat demi portofolio akademik atau karier. Dampaknya, proses pembelajaran seringkali hanya dianggap sekadar formalitas belaka. Fokus berpindah dari mampu memahami dan mengaplikasikan materi menjadi memastikan dokumen itu lengkap.
Dampak negatif dari obsesi sertifikat pun tak terelakkan. Proses pendidikan kehilangan makna ketika hasil lebih dihargai daripada proses. Pola pikir instan juga mendorong perilaku tidak jujur, seperti menyontek atau menjiplak demi nilai akhir. Praktik ini merusak integritas akademik dan etika belajar. Pendidikan pun kehilangan perannya sebagai ruang pembentukan karakter pelajar.
Budaya ini juga membuat suatu persepsi yang keliru dalam menilai kemampuan. Banyaknya sertifikat sering dianggap bukti kecakapan, padahal tidak sedikit peserta yang hanya menjadi “penonton” dalam proses belajar. Karena banyaknya sertifikat dianggap lebih dilihat daripada kemampuan nyata, sehingga kualitas pembelajaran semakin diabaikan.
Selain itu, obsesi sertifikat dapat melemahkan sikap kritis. Ketika tujuan utama hanyalah selembar sertifikat, pelajar tidak terdorong untuk bertanya, berdiskusi, atau menguji gagasan. Proses belajar menjadi pasif dan kehilangan fungsinya sebagai ruang berpikir. Padahal pendidikan adalah ruang proses pembentukan nalar, karakter, dan kompetensi pelajar.
Kondisi ini sejalan dengan pandangan Bryan Caplan dalam bukunya The Case Against Education. Ia menilai pendidikan modern lebih berfungsi sebagai penanda kemampuan bagi pasar kerja. Pendidikan sering kali tidak benar-benar meningkatkan keterampilan peserta didik. Fenomena inflasi sertifikat memperkuat kondisi tersebut. dimana permintaan sertifikat meningkat tanpa diiringi kebutuhan keterampilan yang sepadan.
Pandangan serupa disampaikan Brandon Busteed dalam artikel Forbes. Ia menyoroti bahayanya penekanan berlebihan terhadap diploma atau sertifikat (credential over education). Ini dapat merusak tujuan pendidikan sesungguhnya, sehingga masyarakat mungkin hanya menghargai dokumen daripada kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konseptual.
Obsesi sertifikat juga memperlebar jarak antara pendidikan dan dunia kerja. BPS mencatat ada 9,9 juta Gen Z (usia 15-24 tahun) menganggur, dan salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya soft skill seperti komunikasi dan interpersonal. Kondisi inilah yang menurunkan daya saing mereka di pasar kerja. Padahal, riset global dari Universitas Harvard, Yayasan Carnegie, dan Stanford Research Center menunjukkan 85% keberhasilan kerja lebih banyak ditentukan kemampuan interpersonal. Ini menunjukkan sertifikat tidak selalu menjamin kesiapan kerja, karena kemampuan, pengalaman, dan soft skill justru sering menjadi penentu di lapangan.
Tantangan dalam sektor pendidikan tidak lain mempertahankan arti dari proses pembelajaran di tengah sistem yang masih fokus pada sertifikat dan persyaratan administratif. Proses pendidikan termasuk aktivitas praktik berisiko dipahami sebagai kewajiban administratif, alih-alih sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan. Pendidikan harus mengedepankan proses pembelajaran sebagai fokus utama. Dengan mengevaluasi pemahaman, keterampilan praktis, soft skill, dan kemampuan beradaptasi sebagai penentu hasil dalam pembelajaran.
Sertifikat memang penting, tetapi bukan segalanya. Bagi pelajar dan mahasiswa, yang jauh lebih esensial adalah proses belajar itu sendiri, bagaimana pemahaman dibangun dan keterampilan diasah, bukan seberapa cepat dan banyak sertifikat diperoleh.
Di sisi lain, lembaga pendidikan perlu memperkuat kualitas proses pembelajaran. Pendidikan tidak boleh berhenti pada urusan administrasi. Proses belajar harus relevan dengan kebutuhan nyata. Penilaian perlu menekankan kemampuan softskill, bukan sekadar kelulusan. Dengan demikian, makna proses belajar tetap terjaga.
Pada akhirnya, proses belajar harus dikembalikan sebagai investasi jangka panjang. Sertifikat memang memiliki nilai, tetapi ia tidak berdiri sendiri. Karena kemampuan nyata dan kompetensi itu lahir dan diukur dari proses belajar yang konsisten dan mendalam. Di tengah arus digital yang serba instan, pendidikan harus membentuk nalar kritis dan daya adaptasi tanpa menggerus makna pembelajaran. Maka dari itu pelajar dan mahasiswa perlu menguatkan proses belajar hari ini guna menyiapkan masa depan yang lebih berdaya.