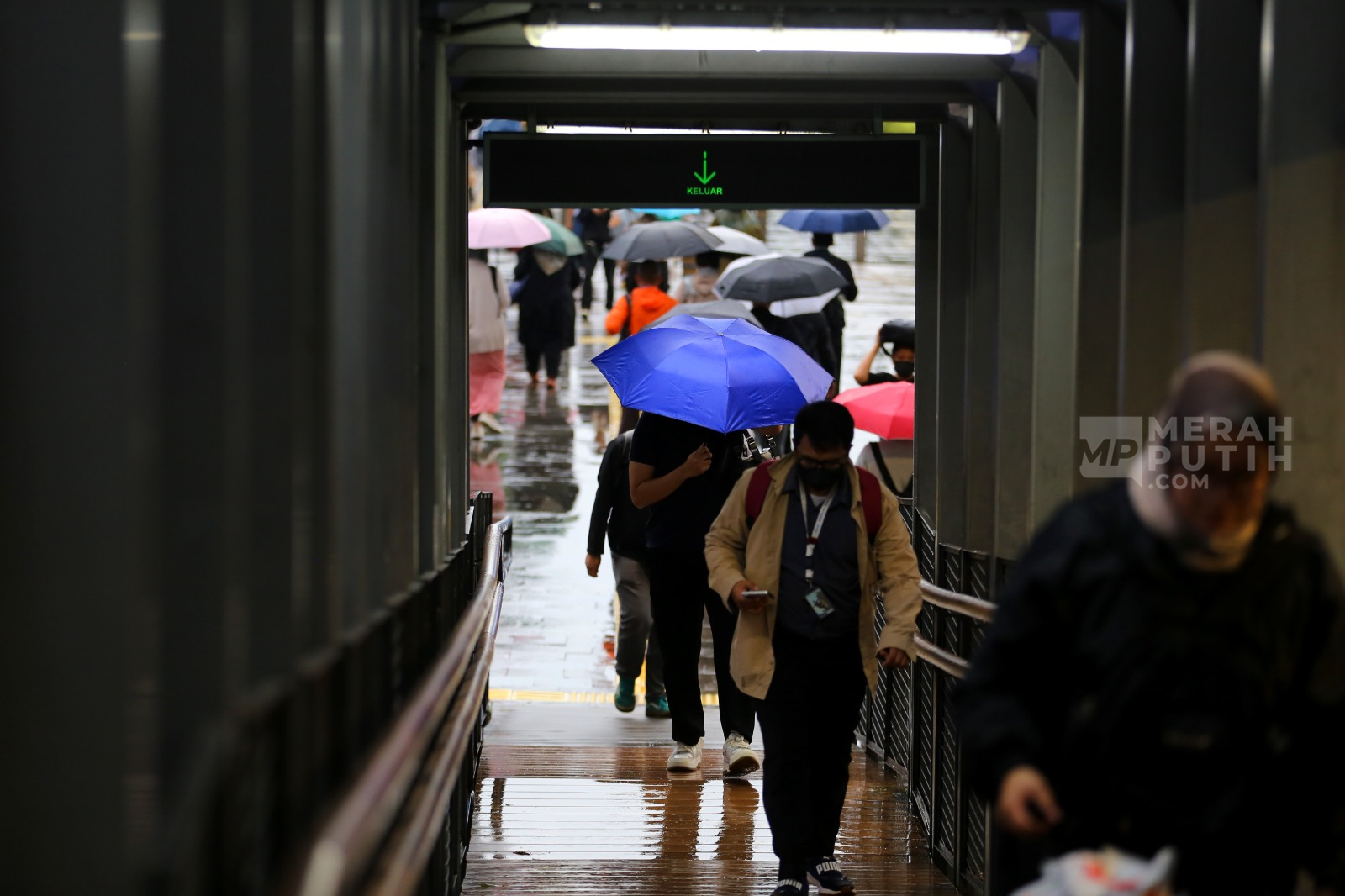Artikel ini tidak dimaksudkan untuk menginspirasi Anda melakukan tindakan serupa. Jika mengalami depresi atau bermasalah dengan kesehatan jiwa, tinggalkan artikel ini dan segera hubungi layanan kesehatan mental terdekat. Kementerian Kesehatan menyediakan layanan kesehatan mental dan bunuh diri di healing119.id
Bunuh diri pada anak adalah satu kasus dengan catatan panjang di berbagai era di seluruh dunia. Penyebabnya tak tunggal sehingga penyelesaiannya tak bisa digeneralisasi. Mengurai masalah kompleks pada diri masing-masing anak menjadi pintu masuk utama.
Di dalam negeri, kasus anak mengakhiri hidup terjadi jauh sebelum internet merebak. Dalam catatan Kompas edisi 2 Agustus 1973, seorang anak perempuan mengakhiri hidupnya karena beban berlapis di Bandung, Jawa Barat.
Ia juga mendapat kekerasan fisik dari ayahnya. Berita tersebut mengabarkan sang ayah melakukan hal tersebut lantaran tak setuju anaknya berpacaran dengan pemuda gondrong.
Di rentang waktu yang tak lama, fenomena anak mengakhiri hidup juga terjadi di belahan dunia lain. Dalam laporan Kompas, 4 Maret 1978, tercatat 784 anak muda di bawah 20 tahun bunuh diri sepanjang 1977 di Jepang.
Laporan tersebut mencatat, 107 kasus bunuh diri karena “dukacita asmara”, hal yang sedikit mirip dengan kasus di Bandung. Laporan itu juga memberi kisi-kisi tentang ketimpangan hubungan antarteman di sekolah.
“Pihak kepolisian mengatakan kasus itu terjadi diantaranya karena gagal menyejajarkan diri dengan teman-teman mereka di sekolah’,” tulis laporan tersebut.
Di tahun 1970-an, angka kasus bunuh diri pada anak di Jepang masih perlu ditelaah lebih dalam. Sebab, setiap kasus punya latar belakang dan kerumitan masalahnya masing-masing.
Laporan Kompas, pada 10 Oktober 1977 mencoba mengurai beberapa penyebab yang mungkin memengaruhi kasus di Jepang. Di kota-kota besar Jepang, baik para pekerja, mahasiswa, hingga murid hidup tergesa.
Kondisi tersebut membuat anak-anak kurang mendapat waktu senggang di luar kegiatan sekolah. Di sisi lain, rumah belum bisa memenuhi kebutuhan kasih sayang. Itu membuat mereka tak bisa bercerita tentang masalah yang dihadapi.
Sebab, di masa itu banyak ayah dan ibu bekerja dari pagi hingga malam. Kondisi itu ditambah dengan banyaknya orang yang menetap di tempat tinggal sempit.
Keterbatasan lahan di kota membuat tempat tinggal sangat kecil untuk satu keluarga, tapi tak diiringi dengan sarana publik untuk pakansi dan bersosialisasi.
Orangtua tak bisa disalahkan karena kondisi kehidupan di kota memaksa mereka bertahan dengan ayah dan ibu bekerja. Artinya, ada banyak lapisan masalah yang akhirnya membuat anak mengakhiri hidupnya.
Dari laporan tersebut bisa dilihat bahwa iklim kerja di kota-kota besar membuat orangtua tak punya waktu membina hubungan dekat dengan anak. Ada faktor jam kerja panjang yang membuat orangtua kehabisan waktu bekerja.
Di sisi lain, faktor upah layak di perkotaan juga menjadi persoalan. Hal tersebut terlihat dari ayah dan ibu yang harus bekerja sehingga anak tak mendapat perhatian khusus. Pemerintah mesti menjamin kehidupan layak para pekerjanya.
Tak hanya berhenti di sana, hubungan sosial anak-anak di sekolah juga menjadi masalah yang perlu diurai dan diawasi. Kemampuan sekolah dalam menavigasi dan mengantisipasi masalah anak di sekolah harus ada jalan keluar.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bunuh diri adalah penyebab kematian ketiga terbesar di kalangan usia 15-29 tahun pada 2021. Dari catatan tersebut, banyak kasus bunuh diri terjadi secara impulsif di saat krisis.
Penyebabnya akibat hilangnya kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup, seperti masalah keuangan, perselisihan hubungan, atau nyeri dan penyakit kronis. Keinginan untuk bunuh diri juga kerap muncul pada orang-orang yang mengalami konflik, bencana, kekerasan, pelecehan, atau kehilangan.
WHO pun menekankan pentingnya untuk tidak menstigma kelompok rentan. Sebab, tingkat bunuh diri tinggi di antara kelompok rentan yang mengalami diskriminasi, seperti pengungsi dan migran; masyarakat adat; lesbian, gay, biseksual, transgender, interseks (LGBTI); dan narapidana.
WHO menyarankan agar mengurai penyebab yang kompleks tersebut di samping melindungi masyarakat yang rentan. Secara umum, WHO menganjurkan untuk membatasi akses terhadap sarana bunuh diri di sekitar komunitas rentan.
Media massa dan media sosial juga diminta untuk mengabarkan laporan bunuh diri yang bertanggung jawab, bukan malah menginspirasi pembacanya. WHO mengedepankan identifikasi dini dan dukungan kepada semua orang yang terdampak bunuh diri dan melukai diri sendiri.
Hal itu bisa dilakukan dengan pemetaan oleh pemerintah terhadap lembaga apa saja yang bisa turut mencegah, menangani kasus, pendampingan, hingga pemulihan kasus bunuh diri.
WHO menyebutnya sebagai kolaborasi multisektor. Ini meliputi pemerintah, orangtua, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi masyarakat, sekolah, hingga masyarakat secara umum.
Oleh karenanya, peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan menjadi penting. Hal ini bisa meningkatkan kepekaan seseorang, misalnya, jika melihat ada yang tak beres dengan anak tetangganya. Pemahaman langkah yang harus diambil, semisal aduan cepat, menjadi hal teknis yang mesti diatur oleh pemerintah.
WHO pun menyatakan perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum hingga penyelenggara negara secara menyeluruh. Hal ini menjadi pondasi pelayanan yang baik terhadap aduan-aduan yang ditangani.
Psikiater sekaligus Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa dr H Marzoeki Mahdi, Bogor, Nova Riyanti Yusuf menyampaikan, ada banyak faktor yang harus diwaspadai yang dapat mendorong keinginan mengakhiri hidup pada anak. Biasanya, beberapa faktor muncul bersamaan sebagai akumulasi dari tekanan yang dialami dan bukan faktor tunggal yang memengaruhi.
Nova menuturkan, salah satu tanda yang harus diwaspadai dari keinginan bunuh diri pada anak ialah sikap anak yang menjadi lebih pendiam atau menarik diri. Pada kasus tertentu, anak cenderung mudah marah atau sangat sensitif.
”Anak yang melakukan percobaan bunuh diri biasanya bukan ingin mati, melainkan ingin penderitaannya berhenti. Maka tugas kita adalah memastikan mereka punya tempat bercerita sebelum sampai pada tahapan itu,” tutur Nova (Kompas, 4/2/2026).
Memahami tanda tersembunyi pada tentu bisa mengurangi potensi anak mengakhiri hidup. Langkah selanjutnya adalah pemerintah mencegah kasus serupa terulang dengan menyelesaikan akar masalahnya. Berkaca dari kasus di Jepang, masalahnya bisa jadi adalah persoalan struktural.
-

/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fphoto%2Fori%2F2021%2F11%2F24%2F1deb96ea-7d8d-45a4-9035-ac309c03b45b.jpg)