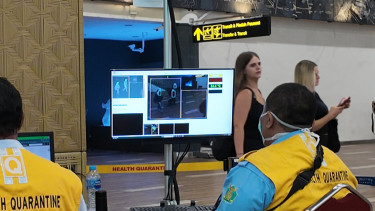Bunuh diri adalah puncak dari masalah kesehatan mental sebuah bangsa. Bunuh diri atau mengakhiri hidup tidak pernah dipicu oleh satu penyebab tunggal.
Karena itu, hilangnya satu nyawa akibat bunuh diri juga menunjukkan adanya persoalan serius dalam tatanan sosial masyarakat. Jika mengakhiri hidup dilakukan anak-anak, maka itu adalah alarm darurat dari kegagalan sistem pengasuhan dan perlindungan anak.
“Bunuh diri pada anak bukanlah keinginan anak untuk mati, tetapi lebih sebagai tanda bahwa anak sudah tidak sanggup lagi menanggung beban emosional dan stimulasi yang dia rasakan,” kata Manajer Pusat Kesehatan Mental Masyarakat atau Center for Public Mental Health (CPMH) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Nurul Kusuma Hidayati, pada Kamis (5/2/2026).
Bunuh diri pada anak merupakan respons keputusasaan atas tekanan emosional yang mereka rasakan dan melampaui kapasitasnya sebagai anak. Mereka kehabisan cara untuk menghadapi tekanan hidup yang mereka alami.
Karena itu, bunuh diri pada anak diyakini sebagai bentuk komunikasi anak untuk meminta tolong agar dikeluarkan dari beban yang mereka rasakan.
Data Pusat Informasi Kriminal Nasional, Badan Reserse dan Kriminal, Polri mencatat sepanjang Januari-7 November 2025 terjadi 1.270 kasus bunuh diri di Indonesia. Sebanyak 7,66 persen atau 97 kasus di antaranya adalah bunuh diri yang dilakukan anak dengan usianya kurang dari 17 tahun.
Dalam konteks generasi, sebagian besar anak-anak pelaku bunuh diri itu termasuk Generasi Alfa atau Gen Alfa. Mereka lahir antara tahun 2010 sampai 2024 atau saat ini berumur antara 1-15 tahun. Umumnya mereka adalah anak generasi Milenial atau Y yang lahir dari 1981-1996 atau saat ini berumur 30-45 tahun.
Gen Alfa merupakan generasi pertama yang sepenuhnya lahir di abad ke-21. Mereka adalah digital natives atau warga digital sejati, yang lahir seiring perkembangan pesat teknologi informasi.
Sejak masih bayi, mereka sudah dikenalkan dengan berbagai perangkat digital. Mereka juga akrab dengan internet, media sosial, hingga aneka gim video sejak usia yang sangat dini.
“Mereka terstimulasi dengan berbagai hal sejak dini. Mereka mengalami tuntutan atau sesuatu yang dipersepsikan sebagai tuntutan yang terlalu banyak dan terlalu dewasa untuk kapasitas kognitif, kemampuan regulasi emosi, dan kemampuan sosialnya yang masih anak-anak,” ujarnya.
Peneliti senior dan pendiri YouthLab Indonesia Muhammad Faisal di Jakarta menambahkan fenomana yang membuat anak-anak terpapar dengan dunia dewasa itu sebut sebagai kidulting.
Fenomena ini membuat anak berinteraksi dengan orang dewasa secara intensif hingga bisa menghayati dan meniru kondisi mental orang dewasa yang sejatinya belum ada di usia anak-anak.
Perjumpaan anak dan orang dewasa itu tidak hanya terjadi di media sosial atau gim video, bahkan beberapa anak dan orang dewasa yang menjadi teman mabar (main bareng) Roblox sudah saling bertemu langsung alias nongkrong bareng. Tak hanya tontonan, lagu, ucapan, hingga cara berpakaian anak-anak pun sudah menyesuaikan apa yang dilakukan orang dewasa.
Namun percampuran anak dengan orang dewasa membuat emosi orang dewasa pun terbawa ke anak.
Hal ini mengakibatkan saat ini mudah ditemukan anak-anak Gen Alfa yang berkata, “Saya frustasi,”, “Aku merasa depresi”, dan hal-hal lain yang tidak jamak pada anak-anak. Stres pada anak umumnya dalam jangka pandek sehingga bisa saja setelah tantrum, sejam kemudian mereka sudah tertawa atau berlarian ke sana kemarin.
Emosi negatif dan mendalam secara terus menerus cenderung terjadi pada orang dewasa, bukan anak-anak. “Namun percampuran anak dengan orang dewasa membuat emosi orang dewasa pun terbawa ke anak,” tambah Faisal.
Sayangnya, kemampuan anak menyaring emosi orang dewasa itu belum ada, mereka belum bisa memahami perasaan orang lain, sehingga salah menyimpulkan karena belum bisa memahami konteks munculnya emosi negatif.
Teknologi digital membuat Gen Alfa mengalami stimulasi berlebihan atas paparan digital, tanpa jeda, sehingga otak mereka sulit dan jarang dalam kondisi tenang atau hening. Bahkan tanpa paparan digital pun, orangtua senantiasa mendorong anaknya untuk aktif, baik otak maupun fisik, seperti dengan mainan edukatif hingga berbagai aktivitas fiisk.
Perpaduan stimulasi berlebih dan kapasitas kognitif-emosi-dan sosial yang belum memadai membuat generasi Alfa mengalami toleransi emosional yang rendah.
Rendahnya toleransi emosional ini membuat anak mudah mengalami emosi negatif berlebih, mudah frustasi, dan suka menuntut pada lingkungan. Anak juga cenderung lebih mudah patah, putus asa, dan menutup atau menarik diri dari dunia sekelilingnya.
“Kondisi itu terjadi bukan karena anak lemah, tetapi lebih karena kapasitasnya belum memadai untuk menampung semua stimulasi yang menghampiri mereka,” kata Nurul.
Hal itu diperparah dengan orang dewasa di sekitar Gen Alfa yang tidak memberi kesempatan atau melatih anak untuk meregulasi emosi yang mereka alami. Saat anak rewel, apalagi saat di tempat umum, orang dewasa di sekitarnya, terutama orangtua, tidak menemani mereka.
Orangtua justru cenderung ‘memadamkan’ atau mengalihkan fluktuasi emosi anak dengan memberikan gawai atau mainan lain agar kegiatan orang dewasa tidak terganggu.
Pengalihan fluktuasi emosi anak sering diulang, bahkan dalam situasi yang sejatinya tidak perlu. Akibatnya, anak-anak Gen Alfa sulit mengenali ragam emosi dan ekspresi emosi yang tepat dan sehat.
“Anak sulit mengekspresikan emosinya karena mereka tidak tahu emosi apa yang dirasakan. Mereka juga kekurangan kosakata untuk menggambarkan emosi mereka,” tambahnya.
Dampak lebih lanjut dari ketidakmampuan anak untuk mengenali emosi dan mengekspresikan emosinya itu lebih rentan pada anak laki-laki. Ekspresi anak laki-laki cenderung berupa ekspresi fisik.
Jika mereka tidak dibiasakan mengobrol, maka mereka akan kesulitan mengekspresikan emosinya dalam kalimat yang tepat dan ekspresi emosinya akan lebih dominan dalam bentuk fisik atau tindakan.
Kondisi itu membuat anak laki-laki cenderung kurang mampu berargumentasi dan condong untuk menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah.
Mereka juga kesulitan untuk meminta pertolongan kepada orang lain. Saat marah, mereka bisa menyakiti orang lain atau justru menyiksa diri sendiri. Cara ini juga membuat kemampuan anak dalam menghadapi masalah juga tidak berkembang.
Perpaduan stimulasi berlebih dan kapasitas kognitif-emosi-dan sosial yang belum memadai membuat generasi Alfa mengalami toleransi emosional yang rendah.
“Mereka tahunya kalau marah akan diluapkan dengan cara yang meledak-ledak, baik ke luar maupun ke dalam,” ujar Nurul.
Dalam konteks anak bunuh diri, lanjut Faisal, bisa jadi anak yang bunuh diri itu sangat disayangi dan diperhatikan oleh orangtua dan orang dewasa di sekitarnya.
Namun, anak tidak bisa menangkap emosi sayang orangtua itu karena memang tidak pernah dilatih dan diajarkan orangtua untuk memahami emosi dan ekspresi emosi orang lain.
Di sisi lain, manusia dari berbagai generasi masih sangat bergantung kepada validasi eksternal. Penghargaan dari orang lain adalah tolak ukur dari keberhasilan.
Saat mereka mengalami kegagalan atau memiliki kekurangan, anak cenderung merasa menjadi beban bagi orang lain, seperti membuat sedih karena membuat ibu pusing atau marah, menyebabkan ayah harus bekerja keras, atau merasa rendah diri karena tidak sepintar kakaknya.
“Anak-anak usia sekolah dasar saat ini menjadi lebih sensitif dibanding generasi-generasi sebelumnya,” tambah Nurul. Sensitivitas berlebih itu menjadi tanda adanya masalah pada kesehatan mental mereka.
Untuk mengatasi berbagai kondisi Gen Alfa yang membuat mereka lebih rentan mengalami depresi, maka dibutuhkan keluarga yang tangguh.
Dalam konsep keluarga tangguh, maka semua hal harus bisa dibicarakan, apapun itu, baik tentang kesedihan, kekecewaan, kegembiraan, kemarahan, harapan, kegalauan, dan semua hal, entah itu yang baik atau buruk.
Konsep keluarga tangguh itu sebenarnya berlaku luas, bukan hanya terhadap orangtua dalam keluarga inti, tetapi semua orang dewasa di sekitar anak, baik yang ada dalam lingkungan rumah maupun sekolah.
Untuk membuat anak mau dan bisa berbicara dengan orang dewasa di sekitarnya, maka diperlukan orang dewasa yang aman (safe adult), lingkungan yang aman (safe place), dan ruang aman (safe space) yang memungkinkan anak memiliki sosok, tempat, dan ruang untuk berbicara apapun, termasuk mengungkapkan keluhan atau kesalahannya.
Keberadaan orang dewasa, lingkungan, dan ruang yang aman akan membuat anak tidak takut bahwa ucapannya akan membuat mereka justru dimarahi atau dihakimi orang dewasa di sekitarnya. Cara ini bisa dikenalkan kepada anak oleh orangtua dengan bercerita tentang kejadian atau emosi yang di alami orangtua sehari-hari. Dengan demikian, saat anak menghadapi masalah, dia pun bisa bercerita kepada orangtuanya.
Ketika anak mengalami patah hati, baik terkait persahabatan, lingkup pergaulan, maupun soal relasi romantis, maka anak pun bisa terbuka dan mampu mengekspresikan emosi ke orangtuanya. Mereka bisa berkata, “I’m not okay. Perasaanku remuk redam, dan masih sangat menyayangi sahabatku. Namun, aku harus move on, meski butuh waktu.”
“Anak yang tangguh bukan berarti mereka tidak menangis atau tidak sakit ketika jatuh, tetapi respon mereka yang terbuka dan mampu mengatakan akan mampu melalui situasi tersebut. Bahkan jika mereka tidak mampu mengelola kesedihannya sendiri, dia tahu bagaimana dan ke mana akan meminta bantuan,” ujar Nurul.
Untuk membuat anak mau dan bisa berbicara dengan orang dewasa di sekitarnya, maka diperlukan orang dewasa yang aman (safe adult), lingkungan yang aman (safe place), dan ruang aman (safe space) yang memungkinkan anak memiliki sosok, tempat, dan ruang untuk berbicara apapun, termasuk mengungkapkan keluhan atau kesalahannya.
Jika anak merasa tidak aman, gelisah, saat berada di dekat orang dewasa, maka itu tanda orang dewasa yang tidak aman bagi anak-anak. Orang dewasa yang tidak aman umumnya adalah mereka yang belum selesai dengan diri mereka.
Mereka biasanya juga sulit terbuka, mengalami tekanan dan tuntutan sepanjang waktu, hingga merasa sering dibanding-bandingkan atau membanding-bandingkan dengan orang di sekitarnya.
Untuk mencegah terus berlanjutnya kasus bunuh diri pada anak membutuhkan ekosistem yang mampu mengasuh dan melindungi anak-anak dengan baik. Semua pihak bisa mengambil peran positif dan konstruktif untuk menjaga dan melindungi anak-anak, bukan saling tuding atau lempar tanggung jawab.
Guna mewujudkan hal itu, lanjut Nurul, orangtua perlu menciptakan waktu luang untuk anak-anak mereka, bukan waktu sisa dari berbagai kesibukan mereka.
Orangtua juga bisa menciptakan ruang bagi anak yang membuat otak mereka tenang, lepas dari segala tuntutan. Ruang dan waktu itu bisa dibentuk melalui obrolan santai dan langsung antara anak dan orangtua, bukan via media sosial, sehingga tercipta pola pikir anak bahwa segala sesuatu itu bisa dibicarakan.
Di sisi lain, sudah saatnya masyarakat kembali aktif menjaga anak-anak di lingkungannya. Budaya kolektif yang makin tergeser oleh budaya individualistis membuat banyak orangtua masa kini cuek dengan kondisi anak-anak di sekitarnya.
Pepatah Afrika menyebut ‘It takes a village to raise a child’, butuh satu kampung untuk membesarkan sau anak. Karena itu, orang dewasa di lingkuangan rumah maupun sekolah perlu sama-sama menjadi orang dewasa yang aman bagi anak.
Sementara itu, Faisal mengusulkan agar pemerintah mengkaji pelaranan media sosial untuk anak sampai batas usia tertentu secara lebih serius. Cara ini sudah dilakukan Australia yang melarang anak memiliki akun media sosial hingga berumur 16 tahun dan Perancis sampai anak berusia 15 tahun.
Negara harus hadir mengingat dampak teknologi digital saat ini sudah masuk jauh ke lingkup rumah tangga dan pengasuhan anak, bukan sekadar dampak pada ekonomi atau pendidikan.
“Jika batasannya sampai anak memahami konteks apa yang dia tonton, maka sesuai teori perkembangan psikologi, pembatasan media sosial untuk anak hingga anak berusia 13 tahun bisa dilakukan.
Namun jika pertimbangan pembatasannya agar anak bisa berdaulat secara emosional saat dibanding-bandingkan dengan orang lain, maka pembatasan terhadap media sosial sebaiknya dilakukan sampai anak berumur 15-16 tahun,” katanya.
Indonesia saat ini memiliki Peraturan PemerintahNomor 21 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan anak atau PP Tunas.
Aturan ini akan membatasi akses anak terhadap platform berisiko rendah hingga usia 13 tahun, platform berisiko kecil dan sedang hingga umur 16 tahun, dan bisa mengakses penuh paltform elektronik umur 16-18 tahun meski harus dalam pendampingan orangtua. Aturan ini ditargetkan berlaku mulai Maret 2026.
Masalahnya, hingga kini pelaksanaan dari aturan tersebut belum jelas. Bahkan di masyarakat, saat orang dewasa menemukan ucapan atau tindakan Gen Alfa yang tidak sesuai konteks atau tidak menunjukkan empati terhadap suatu hal, maka orang dewasa tersebut bukannya meluruskan sikap tersebut, tetapi malah menjadikannya sebagai konten di media sosial karena dianggap lucu.
Negara harus hadir dalam pembinaan karakter bangsa.
Selain itu, saat pembatasan media sosial untuk anak tersebut nantinya dijalankan, maka orang dewasa tidak bisa hanya menyuruh atau melarang anak mengakses media sosial tanpa mereka mau mencontohkannya.
“Negara harus hadir dalam pembinaan karakter bangsa. Jika selama ini pendidikan banyak mengejar kecerdasan atau kepintaran anak, maka saat ini, hal itu sudah tidak diperlukan karena anak bisa pintar dari belajar melalui internet.
Di masa kini dan masa depan, hal yang dibutuhkan adalah anak yang bisa menghadapi tekanan dan bisa keluar dari tekanan” pungkas Faisal.