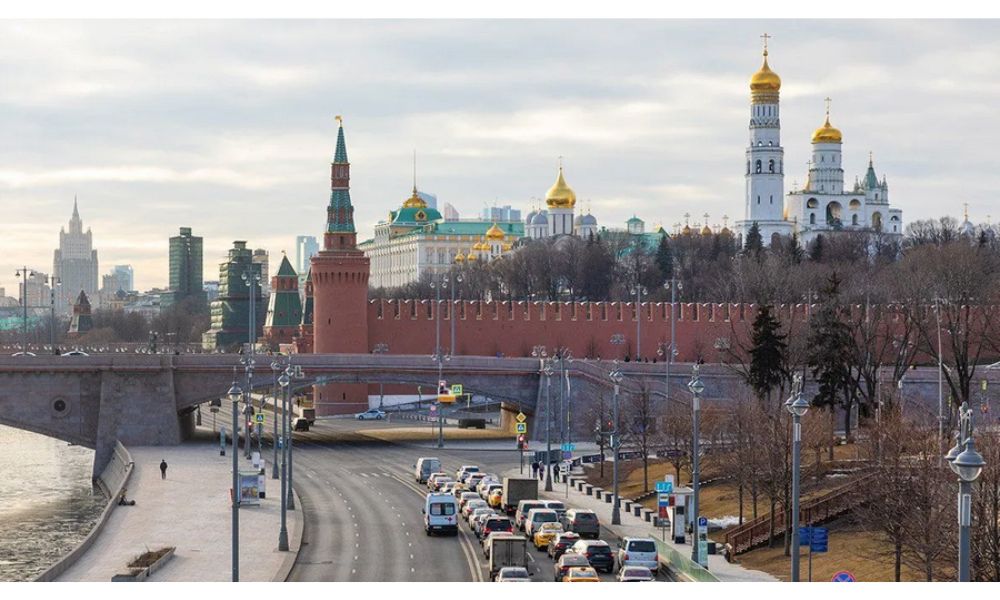JAKARTA, KOMPAS – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meluncurkan kertas kebijakan atau policy paper terkait rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Masuknya militer di ranah sipil ini dinilai inkonstitusional, bahkan mengancam hak asasi manusia dan demokrasi.
Kertas kebijakan ini bertajuk ”Ancaman Menguatnya Militerisme melalui Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Mengatasi Terorisme dan Dampaknya Terhadap Negara Hukum”. Makalah 37 halaman yang disusun oleh setidaknya 24 organisasi sipil ini memaparkan kekhawatiran masuknya militer ke ranah sipil, dalam hal ini penanggulangan aksi terorisme.
Salah satu kekhawatiran terkait masalah formil. Wakil Direktur Imparsial Husein Ahmad menjelaskan, pelibatan TNI untuk urusan dalam negeri, salah satunya penegakan hukum, seharusnya diatur dalam undang-undang. Selain sudah ditetapkan oleh TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000, hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang TNI.
Dalam negara demokrasi, lanjut Husein, pembuatan aturan terkait hajat hidup orang banyak, apalagi yang bisa melakukan pengabaian hak warga negara, semestinya melibatkan banyak orang. Masuknya peran militer ke ranah sipil yang berpotensi menggerus supremasi sipil dan hak asasi manusia seharusnya dijamin dalam undang-undang.
Pengalaman di banyak negara bahkan menunjukkan penggunaan militer dalam keamanan internal dan terutama dalam konteks kontra terorisme itu berisiko melampaui kerangka hukum, mempengaruhi kontrol sipil atas militer, merusak prinsip-prinsip demokrasi, hingga berdampak serius pada penyalahgunaan kekuasaan.
“Dalam konteks terorisme, seharusnya itu, kan, dalam konteks tugas keamanan. Dia (pelibatan TNI) seharusnya diatur dalam level undang-undang, bukan kemudian diatur dalam level perpres, yang dibuat sendiri, ditandatangani sendiri, oleh presiden,” kata Husein dalam diskusi publik peluncuran kertas kebijakan tersebut, Minggu (8/2/2026).
Menurut Husein, perluasan peran TNI ini bisa mencampuradukkan fungsi militer dan penegakan hukum. Selain itu, bisa membuka ruang penggunaan kekuatan militer dalam situasi yang seharusnya ditangani oleh otoritas sipil.
Husein menyinggung doktrin antara militer dengan penegakan hukum. Militer, lanjutnya, adalah fungsi pertahanan dengan menghancurkan target, sementara penegakan hukum itu menangkap dan menyeret ke meja peradilan.
“Polisi saja yang dilatih sebagai penegak hukum, masih banyak dikritik karena pelanggaran HAM. Apalagi tentara yang memang tidak pernah dididik untuk melakukan penegakan hukum,” kata Husein.
Sementara itu, Direktur Raksha Initiatives Wahyudi Djafar - yang juga termasuk dalam koalisi - mengingatkan polemik pelibatan militer dalam penanggulangan terorisme. Seperti yang disebutkan dalam kertas kebijakan, sejumlah studi menunjukkan operasi militer justru menimbulkan konsekuensi inkonstitusional jangka panjang.
Bahkan, kekerasan negara yang berlebihan justru menyediakan narasi ketidakadilan yang mudah dieksploitasi. Di sisi lain, berbagai studi menunjukkan kelompok teroris lebih sering berakhir melalui proses penegakan hukum, delegitimasi politik, dan integrasi ke dalam proses politik dibandingkan eliminasi militer.
“Beberapa studi terbaru memperlihatkan pemberantasan terorisme yang melibatkan militer akan sangat berisiko. Dia meningkatkan korban sipil, memperburuk ketidakpuasan komunitas rentan yang menjadi sasaran ideologisasi teroris, atau bahkan menjadi bahan propaganda. Ini justru malah memperpanjang terorisme itu sendiri,” papar Wahyudi.
Wahyudi mencontohkan, kondisi serupa terjadi di beberapa negara Afrika yang melibatkan militer, di antaranya Burkina Faso, Nigeria, Kenya, dan Mali. Hal ini berujung pada skenario perang tanpa akhir yang merugikan masyarakat.
“Pengalaman di banyak negara bahkan menunjukkan penggunaan militer dalam keamanan internal dan terutama dalam konteks kontra terorisme itu berisiko melampaui kerangka hukum, mempengaruhi kontrol sipil atas militer, merusak prinsip-prinsip demokrasi, hingga berdampak serius pada penyalahgunaan kekuasaan,” kata Wahyudi.
Pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Milda Istiqomah menyoroti perdebatan serius dalam rancangan perpres ini. Dalam menanggapi kertas kebijakan ini, dia melihat perdebatan itu dari perspektif hukum tata negara, hak asasi manusia, bahkan sistem peradilan pidana.
“Ini berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai batas kewenangan militer dalam negara demokratis, dan juga bagaimana implikasi rancangan perpres semacam ini terhadap prinsip supremasi sipil dan juga rule of law,” ujar Milda.
Oleh karena itu, Milda menilai diskursus mengenai pelibatan TNI dalam penanganan terorisme harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Penguatan penegakan hukum sipil menjadi pilihan paling konstitusional dan berkelanjutan dalam menghadapi ancaman terorisme.
“Pendekatan humanis yang selama ini sudah dianggap berhasil selama 20 tahun terakhir ini harus tetap diutamakan. Jika memang tujuan utamanya itu adalah efektivitas, maka memang betul memperkuat kapasitas Polri dan juga BNPT. Itu lebih konsisten dengan karakter tindak pidana terorisme,” ujar Milda.
Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti berharap pemerintah dan para politikus berpihak kepada rakyat. Masyarakat tidak hanya melihat ini sebagai produk perpres, tetapi tentang upaya militerisme masuk ke ranah penegakan hukum.
“Presiden, DPR, politikus, tolong memihaklah kepada rakyat. Kita semua tolong hanya melihatnya seakan-akan hanya tentang terorisme. Terorisme ini memang penting, tetapi mari kita melihatnya dengan kacamata militerisme dan apa itu negara hukum,” ujar Bivitri.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme belum ditandatangani Presiden. Dengan demikian, draf perpres yang beredar masih belum berlaku (Kompas.id, 8/1/2026).
Prasetyo menegaskan, hingga kini belum ada keputusan akhir terkait substansi pengaturan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Oleh karena itu, ia meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan atau membangun kekhawatiran atas kebijakan yang masih dalam pembahasan.
Prasetyo menjelaskan, setiap kebijakan pada akhirnya akan diterapkan secara terbatas dan kontekstual sesuai kebutuhan serta situasi tertentu. Pemerintah pun berkomitmen untuk tidak memberlakukan aturan tanpa batasan yang jelas dan mekanisme pengendalian yang memadai.
Sebagai perbandingan, Prasetyo menyinggung pembahasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang sebelumnya juga memicu kekhawatiran publik. Menurut dia, sejumlah pasal yang dipersoalkan justru dirancang dengan prinsip pembatasan.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2025%2F03%2F25%2Fba9eb8a6-ebc9-4500-a479-cce6559f8f07_jpg.jpg)