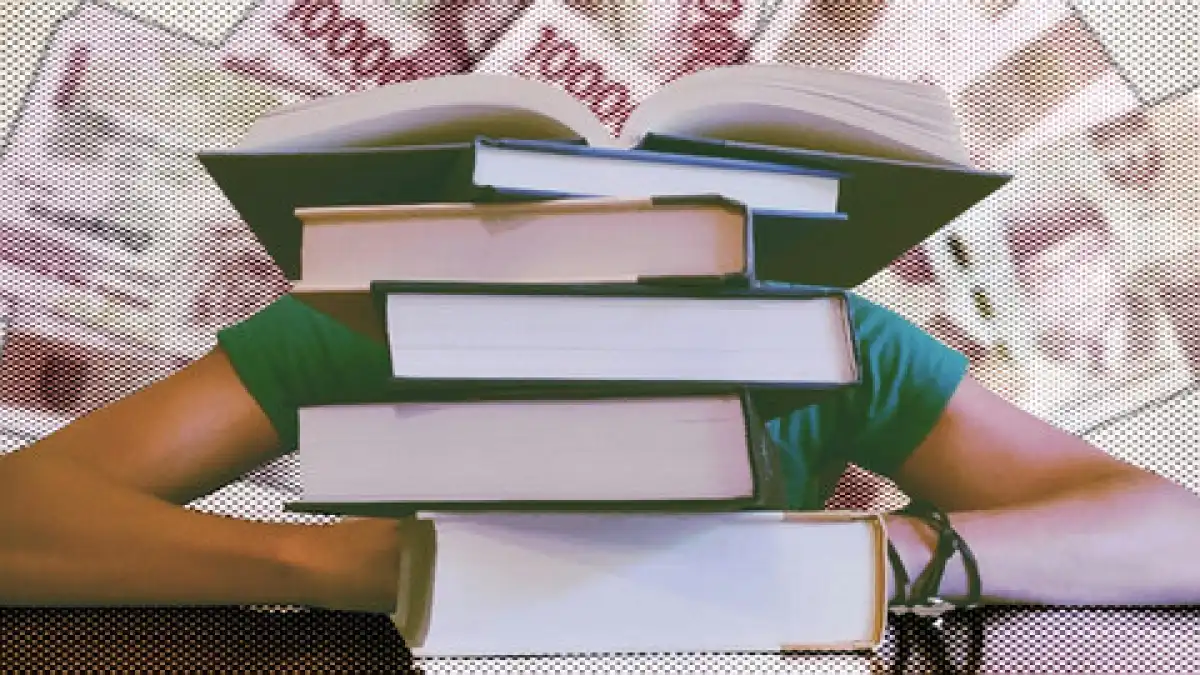Berdasarkan survei di Amerika Serikat dari reviews.com, manusia cenderung membuka gawainya sekitar 186-205 kali setiap harinya. Jika dirata-rata, setiap orang membuka gawai setiap lima menit sekali. Sebanyak 60-75% orang akan merasa cemas jika tak membawa gawainya.
Pernahkah anda merenungkan bahwa di era ini, mindfulness adalah hal yang sangat langka? Pulang bekerja atau sekolah, kita disuguhi iklan-iklan dari papan reklame di jalanan.
Spanduk sekolah, baliho calon pimpinan, berbagai toko-toko yang merknya terpampang dengan kecil sampai besar–bahkan, kedai-kedai kelas menengah sampai atas (yang salah satunya bisa jadi favorit kita) harus kita lewati.
Belum lagi keadaan kendaraan yang macet-padat-merayap di pagi hari saat berangkat maupun saat pulang. Pulang bekerja, kita berharap dapat sedikit tenang dengan membuka gawai.
Secara otomatis, saya sering kali membuka aplikasi merah YouTube, TikTok, Instagram, bahkan Facebook, apalagi WhatsApp—yang saya begitu khawatir tertinggal informasi tentang pekerjaan.
Pulang bekerja atau sekolah, kita seolah tak punya pilihan selain terus terjebak pada pusaran media sosial. Alih-alih menutup gawai dan bercengkrama bersama keluarga, kita merasa memerlukan self-reward dari hasil kelelahan banting tulang karena seharian bekerja.
Tak jarang pula kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk sekedar scrolling hal-hal yang kita anggap telah kita sukai.
Hidup kita seolah tengah dikendalikan oleh benda aneh tetapi dahsyat, sesuatu yang bernama algoritma. Pernahkah kita bahkan berpikir, betapa menderitanya kita selama ini akibat keterikatan yang besar terhadap gawai dan ketergantungan yang besar terhadap media sosial? Betapa singkatnya hidup ini, tetapi betapa miskinnya kita terhadap ketenangan.
Jika kita bandingkan dengan zaman pendidikan muslim tradisional, orang-orang masih bisa menghafalkan Al-Qur’an, karena masyarakatnya dibangun dengan kebiasaan membaca Al-Qur’an.
Tak jarang, para cendekiawan besar atau bahkan anak-anak biasa sudah mampu menghafal Al-Qur’an sejak usia 3-6 tahun karena masyarakatnya pun juga rajin membacanya (bincangmuslimah.com).
Namun di hari ini, anak-anak kita begitu fasih mendengar lagu Tung Tung Sahur atau Ballerina Cappucina yang membuat otak anak-anak kita mengalami brain rot tak berkesudahan.
Hidup kita seolah dipenuhi yang sedang viral ini itu, lalu berganti lagi, dan seterusnya. Hal itu membuat kita mengalami pengelolaan emosi yang dangkal dan terus-menerus menginginkan hormon dopamin sesaat.
Dalam buku Digital Minimalism: Choosing a Focused Life in a Noisy World—yang ditulis oleh Cal Newport pada tahun 2019—gejala sosial ini bukanlah permasalahan satu orang saja.
Hal ini merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam struktur dan sistem masyarakat kita di era teknologi ini. Maka dari itu, memang diperlukan sebuah sistem yang dibangun dari masing-masing individu agar dampak dari internet ini dapat membuat kita jadi lebih bermakna.
Newport menekankan, kita telah mengalami semacam kekacauan digital (digital clutter) dengan menginstalasi banyak sekali aplikasi ke dalam gawai kita.
Jika kita membuka aplikasi semacam WhatsApp atau Telegram, kita terlalu banyak memiliki group chat yang bahkan kita enggan membukanya. Notifikasi terus datang silih berganti—entah dari Shopee, kadang-kadang Instagram, dan lain sebagainya—yang membuat hidup kita terasa penuh di kepala.
Newport—yang merupakan profesor ilmu komputer itu—memberikan saran. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah detoks digital selama 30 hari. Hapus atau uninstall aplikasi-aplikasi yang membuat kita bertapa berjam-jam di depannya.
Jika ia tidak terkait dengan pekerjaan atau keluarga, artinya kita tidak benar-benar membutuhkannya. Hanya gunakan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat dalam pekerjaan atau keluarga.
Banyak pembaca buku Newport yang merasakan manfaat dari detoks digital tersebut, yakni mereka merasa jadi lebih produktif karena tidak terus-menerus membuka aplikasi yang tidak penting itu.
Sikap impulsif terhadap membuka gawai pada waktu-waktu genting akan berkurang dengan sendirinya. Saya juga merasakan manfaat dengan menghapus aplikasi Facebook dan Instagram. Hidup cukup lebih tenang karena tidak merasa bertanggung jawab dengan harus membukanya.
Newport juga menganalisis bahwa masyarakat hari ini mengalami solitude deprivation yang bermakna kekurangan waktu untuk benar-benar sendirian.
Fenomena ini terjadi karena kekosongan kita selama ini selalu diisi oleh layar gawai. Saat makan sendirian di restoran, kita membuka gawai. Saat mengantre bayar di kasir, kita membuka gawai. Saat menunggu cuci mobil, kita membuka gawai. Akhirnya, lama kelamaan kita sangat gelisah jika suatu hari gawai kita tertinggal.
Dampaknya, menurut Newport, jika kita terus-menerus bergantung terhadap gawai dan internet, kita jadi sulit untuk memproses emosi dan merefleksikan perasaan kita sendiri. Kejernihan pikiran menjadi sirna karena otak kita telah dipenuhi berbagai informasi singkat–yang bahkan tidak kita perlukan sama sekali.
Maka dari itu, Newport merekomendasikan untuk mencoba hidup tanpa notifikasi atau layar. Kita bisa berjalan kaki 15 menit tanpa gawai, menulis perasaan dan pikiran kita di jurnal, menyetir tanpa musik, atau sekadar duduk tenang menikmati suara-suara dan pemandangan di sekitar.
Hasil eksperimen Newport juga menarik ketika ia dan beberapa pembacanya mencoba untuk mematikan semua notifikasi di gawai, kecuali hanya untuk telepon keluarga.
Hasilnya, produktivitas menulis dan berkarya mereka meningkat tajam dan rasa tenang pun meningkat. Dengan kata lain, hasil pekerjaan yang sifatnya menciptakan atau kreativitas akan lebih meningkat ketika kita tidak terdistraksi oleh gawai.
Hal ini sangat menarik untuk dapat diterapkan agar kita dapat mengendalikan isi pikiran kita. Tentunya, mentalitas akan lebih terjaga dimulai dari jari kita sendiri.