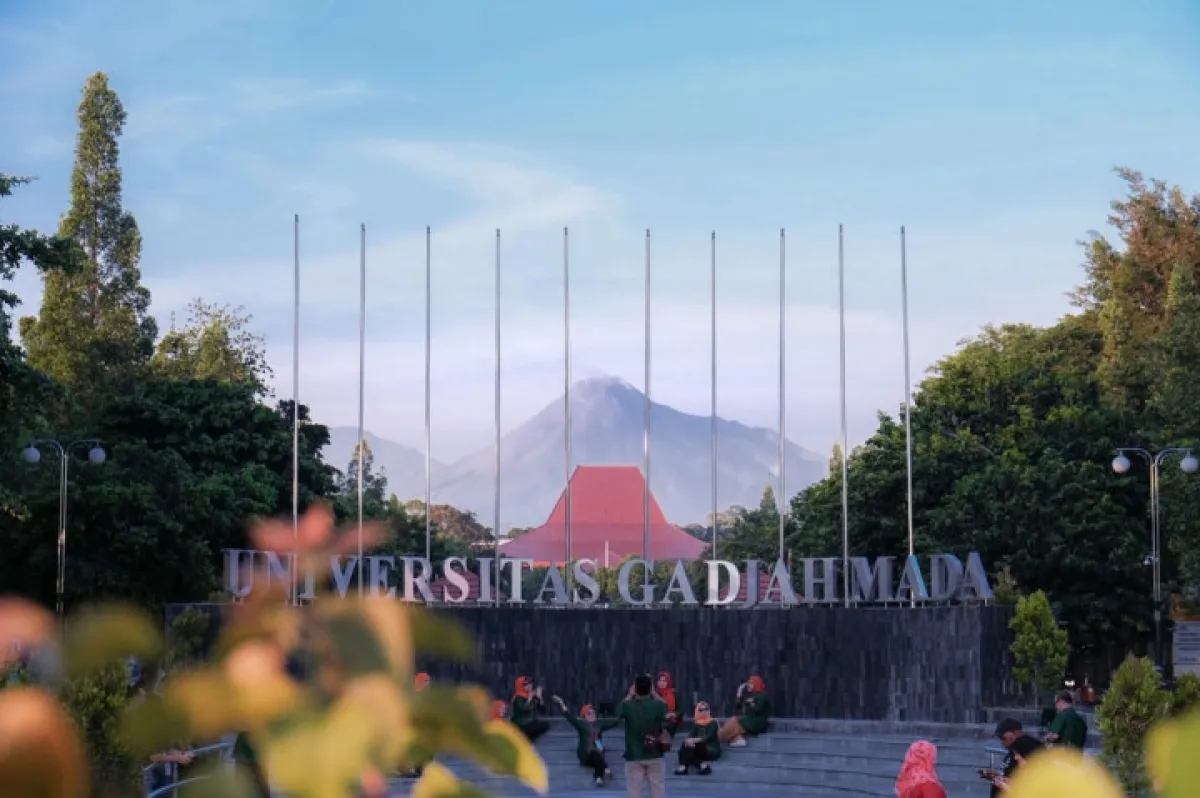Otonomi daerah sudah berjalan lebih dari dua dekade. Namun hingga hari ini, pengelolaan keuangan daerah masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Persoalannya bukan sekadar soal besar-kecilnya anggaran, melainkan juga bagaimana anggaran itu direncanakan, dieksekusi, dan diubah menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu gejala paling kasat mata adalah pola penumpukan realisasi belanja di akhir tahun. Dalam lima tahun terakhir, realisasi belanja APBD secara nasional pada semester pertama rata-rata masih berkisar 30 persen dari pagu.
Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa sebagian besar belanja daerah baru bergerak signifikan pada Triwulan IV. Pola ini berulang dari tahun ke tahun, seolah telah menjadi “tradisi” dalam tata kelola keuangan daerah.
Penyerapan anggaran yang rendah di awal tahun sering kali berakar pada kualitas perencanaan. Tidak sedikit program dan kegiatan yang telah dianggarkan, tetapi belum siap dilaksanakan karena dokumen teknis belum lengkap, proses pengadaan belum matang, atau kesiapan lahan dan desain belum tuntas.
Akibatnya, pelaksanaan menunggu, lalu dikejar waktu di akhir tahun. Dalam situasi seperti ini, kualitas belanja publik menjadi taruhan.
Masalah perencanaan ini berkaitan erat dengan struktur pendapatan daerah. Hingga kini, Transfer ke Daerah (TKD) masih menjadi sumber dominan pendapatan APBD. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di banyak wilayah belum dikelola secara optimal.
Ketergantungan pada transfer pusat membuat ruang fiskal daerah terbatas dan mendorong sikap menunggu. Padahal, daerah dengan PAD yang kuat cenderung lebih fleksibel dan berani dalam mengeksekusi program pembangunan.
Di balik persoalan teknis, ada faktor nonteknis yang sering luput dibahas: ketakutan pejabat daerah terhadap risiko hukum. Dalam berbagai diskusi kebijakan publik, isu ini kerap mengemuka. Penunjukkan sebagai pejabat pembuat komitmen atau pengelola proyek daerah sering dipersepsikan sebagai posisi rawan masalah hukum.
Alih-alih mengambil keputusan, sebagian pejabat memilih bersikap sangat hati-hati, bahkan pasif. Niat menjaga integritas tentu penting, tetapi bila berujung pada stagnasi belanja dan layanan publik, masyarakat yang akhirnya dirugikan.
Tantangan lain datang dari belum meratanya digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah pusat bersama Bank Indonesia dan pemerintah daerah telah mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
Namun, implementasinya masih beragam. Di sejumlah daerah, sistem pembayaran APBD masih dilakukan secara manual atau semi-digital. Proses ini tidak hanya lambat, tetapi juga menyulitkan pengendalian kas dan meningkatkan risiko kesalahan administrasi.
Kondisi tersebut berdampak lanjutan, salah satunya pada pengelolaan perpajakan. Penumpukan pembayaran di akhir tahun—yang diproses secara manual—di beberapa daerah menyebabkan keterlambatan penyetoran pajak oleh bank tempat RKUD berada. Persoalan ini terlihat teknis, tetapi sejatinya mencerminkan lemahnya integrasi sistem keuangan daerah dengan sistem penerimaan negara.
Program Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebenarnya dirancang untuk menjawab sebagian persoalan tersebut. Dengan KKPD, belanja operasional dapat dilakukan lebih cepat, tercatat otomatis, dan lebih akuntabel.
Namun hingga kini, di banyak daerah program ini belum berjalan efektif. Hambatan utamanya bukan pada regulasi, melainkan pada kesiapan SDM, pemahaman mekanisme, dan resistensi terhadap perubahan pola kerja yang sudah bertahun-tahun dijalankan secara manual.
Persoalan berikutnya adalah cara kita menilai kinerja keuangan daerah. Selama ini, ukuran kinerja SKPD masih didominasi oleh satu indikator: realisasi anggaran dibandingkan pagu. Pendekatan ini terlalu sempit.
Ia tidak menjawab apakah perencanaan anggaran sudah realistis, apakah pelaksanaan tepat waktu, dan apakah belanja benar-benar menghasilkan output serta outcome yang diharapkan. Akibatnya, serapan tinggi sering dianggap sukses, meski dampaknya bagi masyarakat belum tentu signifikan.
Di luar belanja, pengelolaan aset daerah juga masih menyimpan banyak potensi yang belum tergarap. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berulang kali mencatat persoalan aset daerah yang tidak tertib administrasi, atau tidak dimanfaatkan optimal.
Padahal, aset daerah—tanah, bangunan, dan infrastruktur—bisa menjadi sumber PAD yang berkelanjutan jika dikelola secara profesional dan transparan.
Semua persoalan tersebut bermuara pada satu faktor kunci: kapasitas sumber daya manusia. Pengelolaan keuangan daerah saat ini menuntut kompetensi yang semakin kompleks. Pengelola keuangan harus memahami regulasi yang dinamis, sistem digital, manajemen risiko, hingga pengukuran kinerja berbasis hasil.
Tanpa investasi serius pada peningkatan kapasitas—melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan sistem insentif yang tepat—reformasi tata kelola keuangan daerah akan berjalan lambat.
Tantangan serupa juga dihadapi oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Skema BLUD dirancang untuk memberi fleksibilitas dan mendorong efisiensi layanan, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.
Namun di lapangan, banyak BLUD masih terkendala budaya birokrasi lama, keterbatasan manajerial, dan sistem pengawasan yang belum adaptif. Potensi inovasi pun belum sepenuhnya terwujud.
Ke depan, pembenahan pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara menyeluruh. Perbaikan kualitas perencanaan anggaran harus menjadi prioritas utama. Digitalisasi perlu dipercepat secara end-to-end, bukan parsial. Perlindungan hukum bagi pejabat yang bekerja profesional dan beritikad baik harus dipertegas.
Selain itu, optimalisasi PAD dan pengelolaan aset perlu dinaikkan kelas menjadi agenda strategis kepala daerah. Dan yang tak kalah penting, pembangunan kapasitas SDM harus dipandang sebagai investasi jangka panjang.
Mengurai simpul persoalan keuangan daerah memang tidak mudah. Namun dengan kepemimpinan yang adaptif, tata kelola yang akuntabel, dan orientasi pada hasil, APBD dapat benar-benar menjadi alat perubahan—bukan sekadar rutinitas tahunan dalam siklus birokrasi.