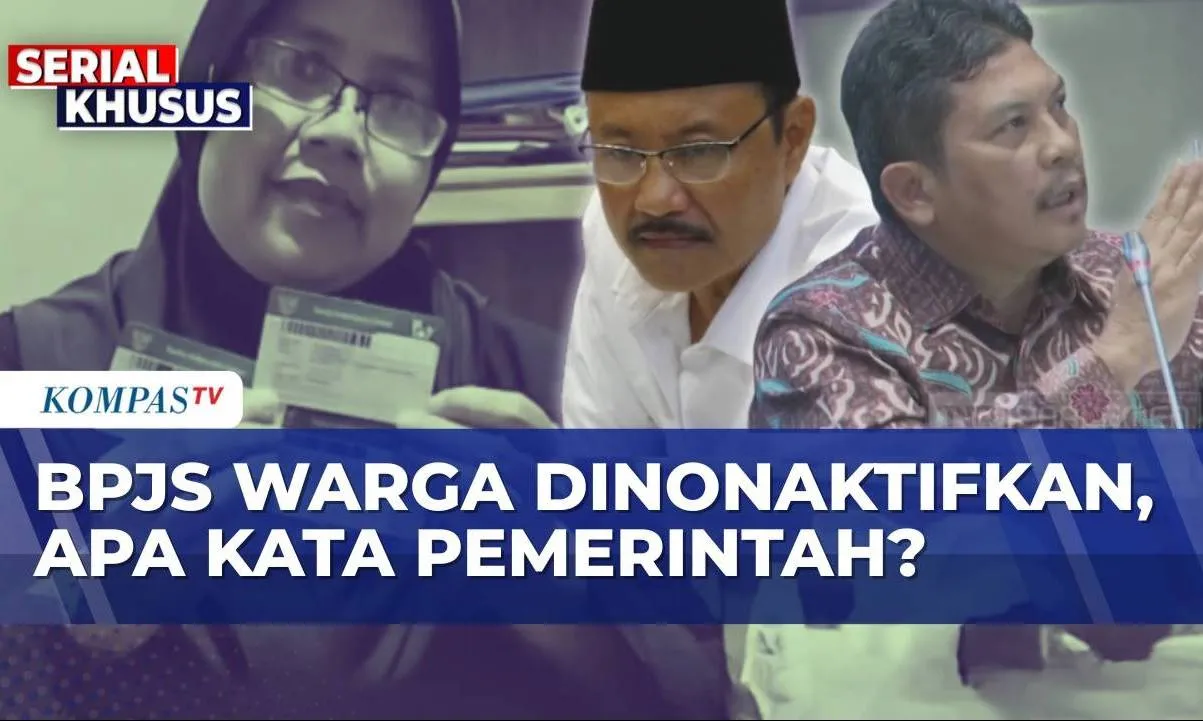Industri otomotif Indonesia masih akan menghadapi jalan berliku tahun ini. Bukan hanya akibat lesunya daya beli masyarakat kelas menengah, melainkan juga ketidakpastian pemberian insentif kendaraan listrik yang beberapa tahun terakhir telah banyak menopang penjualan.
Belakangan ini, di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ada kekhawatiran ruang fiskal pemerintah akan semakin tergerus jika insentif dilanjutkan. Memasuki tahun 2026, pemerintah pun berencana menghentikan sebagian insentif kendaran listrik.
Insentif yang akan dihentikan itu meliputi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) sebesar 10 persen serta pembebasan bea masuk 0 persen untuk kendaraan listrik impor dalam bentuk mobil utuh atau completely built up (CBU) ataupun impor kendaraan rakitan atau completely knocked down (CKD).
Kebijakan ini berpotensi memengaruhi harga jual kendaraan listrik di pasar mulai 2026. Sementara itu, insentif lain seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 0 persen tetap dilanjutkan.
Secara teori, penghentian insentif pajak akan menaikkan harga efektif kendaraan listrik (battery electric vehicle/BEV). Pada segmen yang sensitif terhadap harga, kenaikan beberapa persen saja dapat mengubah keputusan untuk membeli. Bukan hanya kelas menengah, konsumen menengah-atas pun begitu.
Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, struktur pasar saat ini menunjukkan, BEV menguasai sekitar 13 persen pangsa pasar, mobil hybrid 9 persen, dan kendaraan bensin (internal combustion engine/ICE) 78 persen.
Khsusus kendaraan BEV, terjadi lonjakan penjualan dalam setahun terakhir karena ditopang oleh insentif dan masuknya berbagai model kendaraan terbaru.
Tanpa bantalan fiskal, elastisitas permintaan kendaraan akan diuji pada 2026. Penjualan bisa melambat, terutama pada model yang masih berstatus mobil utuh dengan komponen impor tinggi.
Di sisi lain, penghentian insentif itu memberi sinyal disiplin fiskal. Dengan defisit anggaran yang ketat dan kebutuhan belanja prioritas lain, setiap rupiah insentif dituntut memiliki multiplier effect yang jelas bagi ekonomi riil, bukan sekadar mengerek volume impor.
Masalahnya, kontribusi kendaraan listrik terhadap nilai tambah industri domestik belum optimal. Josua memaparkan, sekitar 72,9 persen penjualan EV masih berstatus CBU atau impor utuh. Pada 2025, CBU dari China mendominasi dengan 79,1 persen, disusul Vietnam 20 persen, dan beberapa negara lain.
Tingginya impor CBU ini menunjukkan, meskipun penjualan kendaraan listrik beberapa waktu ini meningkat, dampaknya terhadap industri manufaktur dalam negeri masih relatif terbatas.
Di sinilah dilema muncul. Jika insentif dihentikan, penjualan berisiko turun. Namun, jika tahun ini tetap dilanjutkan tanpa syarat yang ketat, insentif berpotensi hanya mendorong impor dan mempersempit ruang fiskal.
“Kalau insentif dihentikan, harga pasti naik dan akan berdampak pada penjualan tahun ini,” ujar Josua, dalam diskusi bertajuk “Insentif EV Dihapus, Ke Mana Arah Masa Depan Industri Otomotif Indonesia”, di Jakarta, Selasa (10/2/2026). Diskusi itu bagian dari penyelenggaraan Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) pada 5-15 Febuari 2026.
Pada triwulan IV-2025, khususnya Desember, penjualan mobil listrik melonjak tajam. Sepanjang 2025, pasar kendaraan listrik nasional meningkat sekitar 70 persen menjadi 175.000 unit. Lonjakan paling signifikan terjadi pada segmen BEV yang meningkat dari 43.000 unit pada 2024 menjadi 104.000 unit pada 2025 atau tumbuh sebesar 141 persen
Lonjakan tersebut diduga sebagai efek front loading akibat kekhawatiran berakhirnya insentif PPN pada awal 2026. Konsumen mempercepat pembelian sebelum fasilitas fiskal dihentikan dan harga-harga naik.
Sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum menetapkan peraturan insentif baru. Josua pun memetakan tiga skenario yang akan terjadi ke depan.
Pertama, penghentian insentif total tanpa adanya perpanjangan atau insentif pengganti. Dampaknya terhadap harga jual BEV akan cukup besar.
“BEV merupakan salah satu jenis kendaraan yang penjualannya masih tumbuh di tengah tekanan pada penjualan otomotif. (Penghentian insentif) itu berpotensi menekan kinerja penjualan otomotif tahun 2026,” kata Josua.
Kedua, perpanjangan seluruh insentif. Perpanjangan insentif berpotensi dapat mengurangi tekanan terhadap penjualan otomotif tahun ini. Namun, skenario ini kecil kemungkinan ditempuh, mengingat dampak insentif kendaraan impor utuh dinilai minimal terhadap perkembangan industri otomotif domestik.
Josua mengatakan, ruang fiskal pemerintah kini semakin terbatas. Realisasi defisit APBN 2025 bahkan telah mendekati batas aman 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Target penerimaan pajak 2026 dipatok tinggi, sementara belanja untuk program prioritas pemerintah tetap besar.
Skenario ketiga adalah perpanjangan sebagian insentif atau adanya insentif pengganti. Dengan ruang fiskal yang lebih sempit, pemerintah sangat mungkin memberi insentif yang lebih terbatas. Misalnya, insentif untuk pembelian mobil pertama atau insentif dari sisi produsen yang sudah mencapai syarat pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Skema bersyarat ini, menurut Josua, bisa menjadi jalan tengah.
Pemerintah telah menempatkan TKDN sebagai tuas utama pemberian insentif. Ambang TKDN minimum 40 persen pada 2026 akan naik menjadi 60 persen pada 2027 dan ditargetkan naik lagi hingga 80 persen pada 2030. Kenaikan bertahap ini dimaksudkan untuk ’memaksa’ produsen memperdalam basis produksi, bukan sekadar merakit di Indonesia.
Implikasinya jelas. Produsen yang ingin tetap kompetitif harus membangun fasilitas CKD, bahkan full manufacturing (produksi komprehensif dari awal-akhir), di Indonesia. Kuncinya ada pada baterai sebagai komponen dengan porsi biaya terbesar pada EV. Tanpa produksi sel dan modul baterai di dalam negeri, sulit mencapai TKDN tinggi.
Insentif impor CBU yang terlalu lama dikhawatirkan hanya menciptakan euforia penjualan tanpa memperdalam struktur industri domestik.
Sementara itu, Pengamat otomotif Yannes Martinus Pasaribu menilai, jika keran insentif kendaraan impor ditutup, hal itu akan memicu kejutan lonjakan harga pada segmen mobil listrik. Namun, di saat yang sama, itu juga bisa menjadi instrumen seleksi bagi produsen yang serius membangun basis produksi di Indonesia.
Pencabutan insentif CBU akan langsung terasa di harga jual. Harga EV impor bisa melonjak 20–40 persen karena tarif bea masuk dan pajak kembali normal. Segmen kendaraan seharga Rp 150 juta–Rp 400 jutaan berpotensi terkoreksi hingga 30 persen.
Namun, menurutnya, minat beli kendaraan listrik tidak akan hilang, tetapi bergeser. Konsumen yang sensitif terhadap harga kemungkinan beralih ke EV rakitan lokal dengan TKDN lebih tinggi atau ke hybrid electric vehicle (HEV) yang harga dan pasokannya relatif lebih stabil.
Di balik kebijakan tersebut, pemerintah dinilai tengah mengambil “pil pahit” untuk jangka pendek demi tujuan jangka panjang. Insentif impor CBU yang terlalu lama dikhawatirkan hanya menciptakan euforia penjualan tanpa memperdalam struktur industri domestik.
”Ini cara pemerintah memaksa prinsipal asing berhenti sekadar menjual barang jadi. Kalau ingin bertahan, mereka harus bangun pabrik dan menciptakan nilai tambah di sini,” ujarnya.
Kenaikan harga moderat masih mungkin ditekan apabila insentif dialihkan secara selektif ke produksi lokal dengan pemenuhan TKDN tinggi sehingga daya saing tetap terjaga.
Yannes mengingatkan, perancangan insentif kendaraan tidak boleh hanya berorientasi pada penurunan harga sesaat. Skema yang efektif harus memulihkan permintaan sekaligus memperkuat struktur industri.
Ia menilai, fokus jangka pendek seharusnya diarahkan pada segmen terbesar dan paling terpukul, yakni LCGC (low cost green car) dan ICE entry-level yang relatif terjangkau. Segmen inilah yang menopang volume produksi nasional dan menyerap komponen lokal paling besar.
Harga LCGC yang kini menyentuh Rp 190 jutaan dinilai sudah terlalu tinggi bagi kelas menengah bawah, apalagi di tengah suku bunga kredit yang masih menekan. Padahal, sekitar 80 persen pembelian mobil di segmen ini bergantung pada pembiayaan.
“Perpanjangan PPnBM DTP (pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah) untuk LCGC/ICE, relaksasi pajak daerah, dan subsidi bunga kredit sangat dibutuhkan agar cicilan turun nyata,” kata Yannes.
Namun, ia menekankan, insentif tersebut harus bersifat temporer dan terukur. Jika penjualan mulai stabil, fasilitas harus dikendalikan agar tidak menciptakan distorsi baru.
Di saat bersamaan, kendaraan LCGC perlu didorong agar kompatibel dengan bahan bakar campuran bioetanol 10–20 persen, sehingga tetap sejalan dengan target penurunan emisi karbon hingga 2030.
Produsen yang hanya mengandalkan impor tanpa basis produksi riil akan tersingkir oleh dampak kenaikan beban fiskal.
Untuk kendaraan listrik dan hybrid, Yannes menilai insentif fiskal tetap perlu dilanjutkan. Namun, insentif itu harus berbasis peningkatan TKDN sesuai peta jalan yang telah ditetapkan. Skema ini penting untuk melindungi industri komponen tier 2–4 yang saat ini tertekan akibat penurunan utilisasi pabrik.
”Jangan lagi memberi ruang impor CBU yang berkepanjangan. Insentif harus dikaitkan langsung dengan realisasi investasi dan kedalaman rantai pasok,” ujarnya.
Yannes juga mendorong integrasi kebijakan fiskal dengan reformasi pajak daerah serta penurunan bunga kredit agar manfaat insentif benar-benar terasa di cicilan konsumen.
Indikator paling krusial bagi kesehatan industri otomotif 2026 bukan sekadar angka penjualan, melainkan tingkat utilisasi pabrik.
“Angka sales bisa terlihat tinggi, tetapi kalau didominasi CBU, tidak ada nilai tambah bagi pekerja lokal. Utilisasi pabrik di atas 60 persen adalah titik aman. Di bawah itu, ancaman pengurangan tenaga kerja nyata,” ujarnya.
Utilisasi yang sehat mencerminkan berputarnya rantai pasok ribuan vendor tier-1 hingga tier-3. Jika pabrik sibuk memproduksi untuk pasar domestik dan ekspor, denyut manufaktur terjaga dan ekonomi riil bergerak.
Dalam dua tahun terakhir, agresivitas merek China dalam memanfaatkan insentif impor CBU telah mempercepat penetrasi pasar. Namun, Yannes melihat fase tersebut hanya sebagai akselerasi jangka pendek.
Ke depan, regulasi diperkirakan akan memperketat saringan melalui kenaikan bertahap TKDN menuju 60 persen dan 80 persen. Produsen yang hanya mengandalkan impor tanpa basis produksi riil akan tersingkir oleh dampak kenaikan beban fiskal.
Dalam konteks ini, merek yang telah lebih dulu berinvestasi memiliki posisi strategis. Hyundai, misalnya, dinilai relatif siap menghadapi pengetatan TKDN karena telah membangun pabrik dan ekosistem baterai di dalam negeri.
Sebaliknya, pemain baru asal China berpacu dengan waktu untuk merealisasikan komitmen investasi fisik, seperti pembangunan pabrik di Subang, agar tidak terdampak regulasi yang semakin ketat.
“Pemerintah pada akhirnya berpihak pada entitas yang melakukan pendalaman industri nyata, bukan sekadar berdagang,” kata Yannes.
Arah kebijakan ini, meski terkesan ”keras” untuk jangka pendek, bertujuan membentuk struktur pasar jangka panjang yang bertumpu pada efisiensi manufaktur domestik dan kedalaman industri komponen, bukan sekadar perang harga impor.
Pengetatan ini justru menguntungkan pemain yang telah menanamkan investasi lokal dan membangun rantai pasok baterai. Sementara, bagi pemerintah, taruhannya jelas, yaitu menjadikan transisi kendaraan listrik sebagai pintu masuk hilirisasi industri, bukan sekadar mengganti sumber tenaga kendaraan.
Kebijakan insentif yang tepat sasaran, disiplin fiskal, serta konsistensi regulasi akan menentukan apakah industri otomotif Indonesia sekadar menjadi pasar besar atau bakal benar-benar naik kelas menjadi basis produksi regional berdaya saing tinggi.