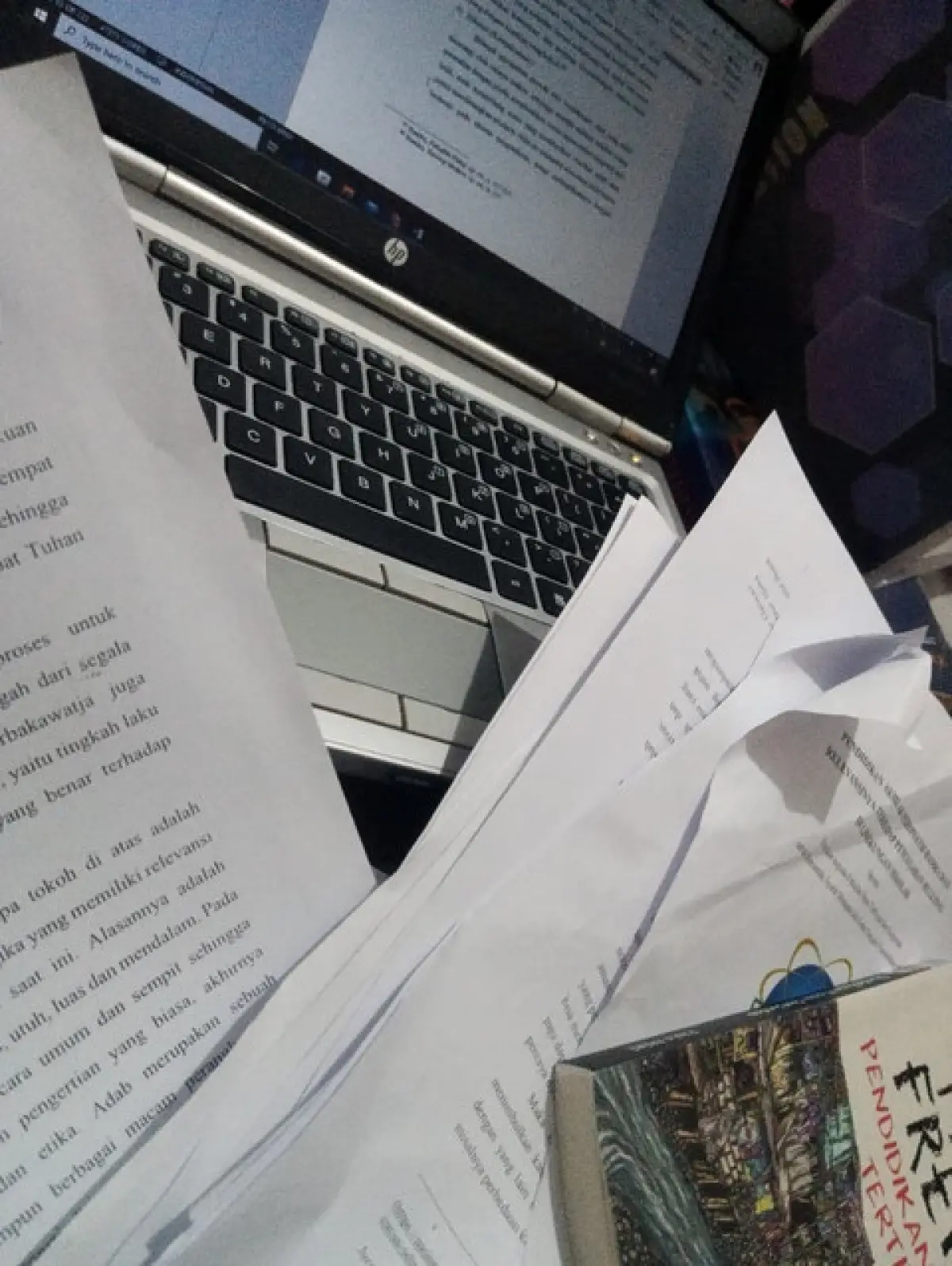Di balik menjulang megahnya gedung-gedung kampus, terdapat satu momok seram yang namanya selalu rutin disebutkan oleh mahasiswa setengah dasawarsa, alias tingkat akhir. Kita dengan sadar menyebutnya sebagai “skripsi”. Tugas akhir bagi mahasiswa ini, yang sejatinya hadir sebagai evaluator kompetensi atas bertahun-tahun pengalaman belajar, kini tidak lagi dipersepsikan demikian. Narasinya berubah menjadi semakin menakutkan, bahkan kerap dianggap sebagai monster yang siap menenggelamkan kewarasan, kebebasan, dan seluruh bentuk keriangan dari wajah-wajah yang sejatinya tak pernah benar-benar siap akan kehadirannya.
Namun, mari kita berhenti sejenak dari stigma tersebut dan mulai berkaca dengan sejujur-jujurnya. Apakah kehadiran skripsi memang sedemikian kejam, atau justru ketakutan yang huru-hara ini hanyalah tunas yang tumbuh subur dari benih kebodohan yang bertahun-tahun kita sirami secara rutin di kelas-kelas kampus?
Saya rasa istilah “menabung kebodohan” terdengar lebih sopan jika memang pilihan kedua dari pertanyaan di atas yang kita sepakati bersama. Istilah ini merupakan metafora paling akurat untuk menjewantahkan realitas pendidikan tinggi kita hari ini. Ketakutan atas tugas akhir tidak lain menyerupai kepanikan seorang debitur yang terkencing-kencing karena sadar bahwa tagihan utang intelektualnya telah jatuh tempo, sementara saldo di kepalanya masih kosong melompong.
Anatomi Kelalaian dan Akumulasi KecuranganSelama tujuh semester, banyak mahasiswa tertidur lelap dalam rasa nyaman yang palsu. Mereka hadir di kelas hanya sekadar menggugurkan kewajiban absensi, sementara kesadaran untuk benar-benar belajar melayang entah ke mana. Tugas-tugas kuliah diselesaikan dengan mentalitas copy-paste atau lebih parah lagi, berlindung di balik punggung teman dalam tugas kelompok dengan cara sekadar menitipkan nama. Di sisi lain, inflasi nilai (grade inflation) membuat IPK di atas 3,8 bertebaran seperti kapas, menciptakan ilusi kompetensi. Mereka merasa aman karena mata mereka telah dibutakan oleh transkrip nilai yang tampak cantik.
Sayang seribu sayang, skripsi adalah auditor yang kejam. Ia tidak bisa disuap, apalagi diakali, dengan presensi atau kerja kelompok. Ketika momen penghakiman tiba di ruang sidang, “tabungan kebodohan” itu seketika pecah tanpa diminta. Dosen kerap menemukan mahasiswa yang gagap menjelaskan metodologi dasar, bingung menautkan alur logika judul yang mereka tulis sendiri, bahkan lebih parahnya lagi, tidak ingat judul skripsinya. Mereka bukan takut pada dosen penguji, mereka takut pada fakta bahwa pakaian intelektual mereka sedang dilucuti hingga tak bersisa pada hari itu.
Akumulasi kepanikan ini ditangkap dengan jeli oleh pasar. Di lorong-lorong digital yang sunyi, industri “joki skripsi” telah berevolusi dari bisnis sampingan menjadi korporasi raksasa pada periode 2025–2026. Mereka beroperasi terang-terangan, lengkap dengan layanan pelanggan 24 jam dan jaminan “bimbingan sampai lulus”. Tarifnya pun variatif dan sistematis. Sebagai contoh, untuk skripsi jurusan sosial-humaniora di Jawa Tengah, tarif berkisar antara Rp2,2 juta hingga Rp3,3 juta.
Namun, bagi mahasiswa teknik yang enggan berpusing-pusing, harganya jauh lebih premium. Mahasiswa Teknik Informatika kini bahkan dapat membeli paket lengkap dengan koding berbasis AI seharga Rp4 juta hingga Rp7 juta atau lebih. Ini tak lagi dapat disebut kenakalan remaja; ini adalah prostitusi akademik yang terstruktur.
Situasi ini kian diperparah oleh sinisme Generasi Z. Data menunjukkan bahwa 51% Gen Z menganggap gelar sarjana mereka sia-sia. Mereka termakan narasi “skill lebih penting daripada ijazah”, namun keliru dalam menerapkannya. Alih-alih mempelajari keterampilan secara otodidak dan serius, mereka justru menanggalkan pembelajaran akademik sama sekali. Kehadiran AI, seperti ChatGPT dan sejenisnya, yang seharusnya berfungsi sebagai asisten riset, malah disalahgunakan menjadi joki gratis. Mahasiswa mampu menghasilkan esai yang tampak indah dan profesional melalui tangan-tangan mesin dalam hitungan detik, sementara otak mereka mengalami atrofi, alias lumpuh karena tidak pernah dilatih berpikir kritis.
Dampaknya kejam dan nyata. Kita akhirnya memanen pengangguran terdidik secara besar-besaran. Data BPS November 2025 mencatat bahwa penyumbang pengangguran terbesar justru berasal dari lulusan SMK dan Universitas (S1), dari total 7,35 juta pengangguran. Pasar kerja menolak mereka bukan karena tidak membutuhkan sarjana atau tenaga profesional, melainkan karena muak dengan sarjana kosong yang tidak cakap dan tidak kompeten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pekerjaan.
Kesimpulan: Tagihan yang Tak TerhindarkanPerjalanan menelusuri fenomena ini membawa kita pada satu konklusi pahit: ketakutan terhadap skripsi merupakan tagihan yang sah dan mutlak atas kelalaian di masa lalu. Skripsi menjelma menjadi monster bukan karena ia ganas, melainkan karena mahasiswa menghadapinya dengan tangan kosong, tanpa persiapan apa pun.
Sejatinya kita semua sedang berada di persimpangan jalan. Jika budaya "menabung kebodohan" ini masih terus dipelihara, visi Indonesia Emas 2045 harus kita terima bersama jika harus berakhir menjadi Indonesia Cemas, dipenuhi oleh jutaan sarjana kertas yang relevan secara administrasi namun usang di dunia nyata.
Bagi mahasiswa, pesan ini adalah alarm keras. Berhentilah menyalahkan dosen “killer”, sistem yang dianggap ribet, atau berlindung di balik isu kesehatan mental untuk membenarkan kemalasan. Rasa sakit saat mengerjakan skripsi adalah rasa sakit dari otot mental yang sedang dilatih. Hadapilah. Lebih baik berdarah-darah di perpustakaan, di hadapan mesin ketik, dan lulus dengan kepala tegak sebagai pemikir mandiri, daripada lulus mudah lewat jalur belakang, tetapi menjadi pecundang seumur hidup di pasar kerja. Lunasi utang intelektualmu sekarang, sebelum kehidupan menagihnya dengan bunga yang jauh lebih mencekik.