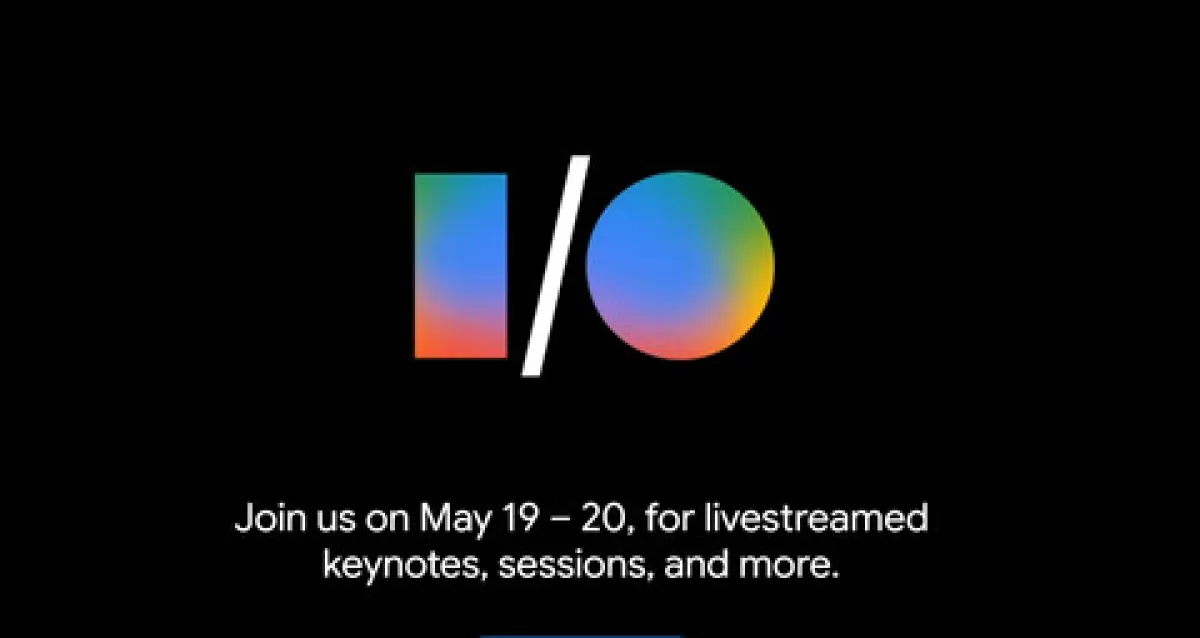BUKAN dongeng, bukan sulap. Ini pernyataan yang benar-benar diucapkan oleh seorang terdakwa kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel menyebut OTT sebagai "Operasi tipu-tipu yang dilakukan oleh para content creator yang ada di Gedung Merah Putih" (Metrotvnews.com, 26/1/2026).
Gedung Merah Putih merujuk kantor KPK, lokasi yang dulu amat ditakuti para maling, pencuri, garong, penilep, pengutil, penggasak uang negara--untuk meminjam istilah harian Kompas kepada koruptor pada dekade 1960-an.
Dan Noel, yang terjerat dugaan pemerasan dalam sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan, menantang, "Hukum mati saya kalau terbukti korupsi. Tapi jika tidak, hukum saya seringan-ringannya" (Hukumonline, 27/1/2026).
Menyamakan OTT sebagai 'operasi tipu-tipu' adalah serangan Noel kepada KPK. Sementara tantangannya agar memberi hukuman mati menunjukkan konsistensi Noel membela ide menghukum mati kepada koruptor.
Ini pun tidak bisa dilakukan semena-mena, ada kategori dan kemendesakan serta kedaruratannya untuk menghukum mati koruptor.
Pasal 2 ayat 2 UU 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebut hukuman mati dapat dijatuhkan dalam "keadaan tertentu".
Noel menyebut soal hukuman mati untuk meyakinkan publik bahwa ia tidak korupsi. Persidangan adil, terbuka, dan tidak digandoli intensi apapun akan membuktikan dakwaan kepada Noel.
Satu yang bikin masygul justru tudingannya bahwa OTT adalah 'operasi tipu-tipu'. Ini serangan serius kepada KPK untuk membuktikan hal itu tidak berdasar dan tidak benar.
Buat saya tudingan keras kepada KPK ini membuka lembaran baru ihwal komisi yang lahir tahun 2003 tersebut.
Baca juga: Kontroversi Pemanggilan MKMK oleh DPR
Di masa sebelum Undang-Undang KPK direvisi tahun 2019, tersangka, terdakwa dan terpidana korupsi tak berani menyerang komisi antikorupsi yang disegani, dihormati dan jadi sekrup penting dalam memberantas korupsi selepas rezim otoriter runtuh tahun 1998 itu.
Pada 9 Maret 2012, seorang ketua umum partai politik yang saat itu menjadi pilar penting pemerintah berujar, "Satu rupiah saja Anas (Urbaningrum) korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas".
Ucapan itu bukan serangan, melainkan tantangan kepada KPK untuk membuktikan hal sebaliknya.
Di pengadilan tipikor, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 57,59 miliar dan 5,26 juta dolar AS.
Hakim menyebut ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi, yakni menerima hadiah dari sejumlah proyek-proyek pemerintah dan tindak pidana pencucian uang (Hukumonline, 24/9/2014).
Ketua KPK saat kasus Hambalang mencuat adalah Abraham Samad, seorang tokoh yang belakangan di depan Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya negeri kita kembali pada UU KPK sebelum direvisi di masa Joko Widodo tahun 2019.
Setelah revisi itu, KPK dinakhodai Firli Bahuri (2019-2024) dan Setyo Budiyanto (2024-2029). Pegiat antikorupsi mempertanyakan independensi KPK setelah payung hukumnya direvisi.
Pasal 3 UU Tipikor contohnya diubah sehingga berbunyi, "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun" (UU 19/2019).
Hidup adalah misteri. Dan tindakan merevisi UU KPK, yang jelas-jelas telah menjadi sandaran ketangkasan dan kelugasan komisi itu dalam memberantas korupsi, juga sebuah misteri yang belum terpecahkan sepenuhnya.
Saya masih ingat, hari itu, 1 Oktober 2019, kami kru "Special Interview with Claudius Boekan" yang tayang di sebuah stasiun televisi melangkah ke ruangan Profesor Azyumardi Azra di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat.
Masa itu adalah masa yang genting, terutama dalam bab pemberantasan korupsi di negeri kita. Gelombang demonstrasi mahasiswa di sejumlah kota meletus, mengingatkan pada tahun-tahun akhir Soeharto, 1997-1998. Waktu itu mahasiswa menolak revisi UU KPK.
Sebagian media menulis gelombang demonstrasi mahasiswa saat itu, terutama di bulan September 2019, cuma kalah gede dan massal dari demo mahasiswa di ujung kekuasaan Soeharto, Mei 1998.
Demo tinggal demo. Pemerintahan Joko Widodo dan DPR tidak mendengar. DPR mengesahkan revisi UU KPK yang justru melemahkan Komisi Antirasuah itu.
Seluruh ikhtiar dilakukan komponen civil society untuk menawar. Salah satunya muncul dalam pertemuan 42 tokoh dengan Presiden di Istana Negara, Jakarta, 26 September 2019.