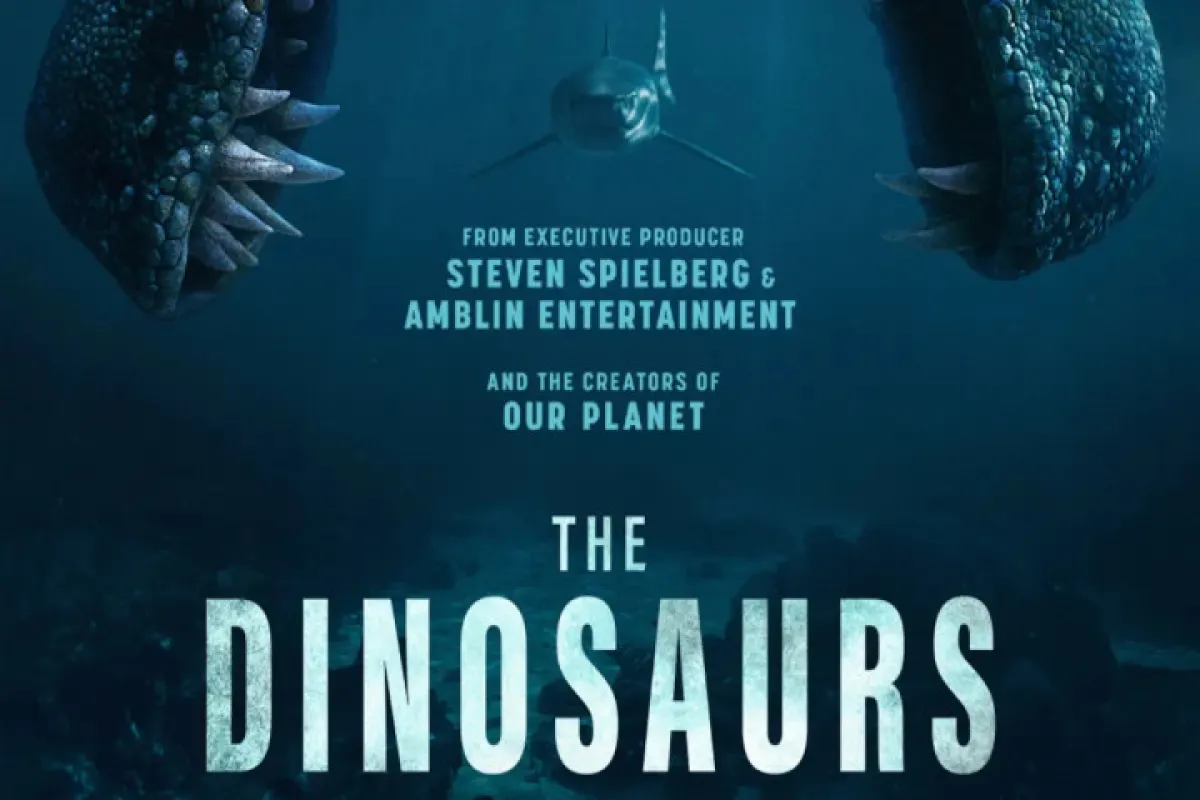Di aula megah Konferensi Keamanan Munich, gema perdebatan tentang masa depan keamanan transatlantik kembali terdengar nyaring. Sejak 1963, forum ini menjadi barometer hubungan Eropa dan Amerika Serikat—kadang penuh harapan, kadang sarat ketegangan. Pada tanggal 13–15 Februari 2026 lebih dari 100–200 pejabat tinggi dan perwakilan diplomatik dari banyak negara bertemu untuk membahas isu keamanan global, persaingan kekuatan besar, dan perubahan geopolitik. Mereka berkumpul dengan kesadaran yang sama: dunia telah berubah, dan Eropa tak lagi bisa merasa nyaman dalam kepastian lama.
Amerika Serikat masih menempatkan lebih dari 80.000 tentaranya di Eropa dan sejak 2022 telah menggelontorkan lebih dari 75 miliar dolar AS untuk mendukung Ukraina. Namun di balik komitmen itu, terselip pertanyaan yang semakin sulit dihindari: sampai kapan Eropa dapat sepenuhnya bergantung pada Washington? Ketidakpastian politik domestik Amerika memicu refleksi mendalam mengenai pembagian beban dan arah strategis baru. Solidaritas lama kini diuji oleh realitas baru.
Kesadaran pertahanan pun bangkit. Pada 2024, 23 dari 32 negara NATO akhirnya memenuhi target belanja militer 2 persen dari PDB—sebuah tonggak yang lama tertunda. Jerman, misalnya, meningkatkan anggaran pertahanannya dari 35 miliar euro pada 2014 menjadi lebih dari 90,6 miliar euro pada 2024. Uni Eropa turut meluncurkan inisiatif miliaran euro untuk memperkuat industri pertahanan bersama. Namun otonomi strategis Eropa masih jauh dari tuntas. Tanpa kapasitas inti seperti transportasi udara strategis dan pertahanan rudal yang memadai, bayang-bayang ketergantungan pada Amerika tetap membentang panjang.
Di luar perang Ukraina, persaingan sistem antara Amerika Serikat dan Tiongkok semakin mempertajam kontur tatanan global. Perdebatan di Munich tak lagi semata soal tank dan aliansi, tetapi juga rantai pasok, cip semikonduktor, dan keamanan ekonomi. Tiongkok kini menjadi mitra dagang terbesar Uni Eropa, sementara lebih dari 90 persen semikonduktor tercanggih diproduksi di Asia Timur—sebuah ketergantungan strategis yang tak bisa diabaikan.
Dalam keamanan ekonomi, Eropa terhubung erat dengan Beijing; dalam arsitektur pertahanan, ia tetap bertumpu pada Washington. Di antara dua tarikan besar inilah Eropa berdiri—mencari keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan jaminan keamanan. Makna keamanan pun meluas: stabilitas nasional kini tak hanya dijaga oleh serdadu, tetapi juga oleh pelabuhan, kabel data, dan pabrik cip.
Tatanan keamanan global berada di bawah bayang-bayang persaingan sistem AS-Tiongkok. Yang berbicara dalam tatanan ini bukan lagi geopolitik tradisional, melainkan kompetisi sistemik. Bahaya dari kompetisi sistemik ini bermuara pada fragmentasi blok-blok teknologi dan ekonomi yang menyimpan daya destruktif bagi tatanan keamanan dunia secara keseluruhan. Bagaimana dengan posisi Eropa yang sepertinya terjepit di antara ketergantungan ekonomi dan payung keamanan? Bagaimana Eropa mendesain strategi politiknya, supaya di satu pihak ia tetap menjaga akses pasar dan investasi dari Beijing, sementara di lain pihak ia juga harus mempertahankan komitmen keamanan trans-Antlantik dengan Washington?
Di tengah pusaran itu, migrasi kembali menjadi ujian solidaritas internal. Gelombang 2015/2016 yang membawa lebih dari 2,5 juta permohonan suaka di Uni Eropa meninggalkan jejak politik yang panjang. Tahun 2023 mencatat lebih dari satu juta permohonan baru, menegaskan bahwa migrasi bukanlah krisis sesaat, melainkan dinamika struktural.
Para pendukung menekankan kewajiban kemanusiaan dan kebutuhan demografis benua yang menua. Para kritikus menyoroti integrasi yang timpang, tekanan pada pasar tenaga kerja, dan polarisasi politik yang menguat. Migrasi menjadi cermin yang memantulkan ketakutan sekaligus harapan—serta keterbatasan Eropa dalam merumuskan kebijakan bersama yang konsisten.
Kompleksitas persoalan migrasi di Eropa diperumit lagi dengan diskusi tentang realitas pemenuhan tanggungjawab terhadap pertahanan. Alokasi 2 persen PDB bagi belanja militer setiap negara anggota NATO malah terseret dalam praktik pemenuhannya. Tetapi persoalan yang lebih mendasar sebenarnya bukan terletak pada ketidakseimbangan kontribusi di antara sekutu ini, melainkan pada minimnya visi strategis, industri pertahanan, serta koordinasi politik di internal Eropa. Defisit ini sangat dirasakan pada invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022—sebuah wake-up call bagi Eropa untuk memperbaiki diskursus politik internal, terutama yang berhubungan dengan solidaritas dan kedaulatan.
Ujian lain hadir di ranah energi dan iklim. Ambisi Green Deal menuju netralitas karbon pada 2050 menjanjikan transformasi hijau yang visioner, namun juga memunculkan risiko ekonomi dan keamanan pasokan. Penutupan reaktor nuklir terakhir Jerman pada 2023 memicu perdebatan sengit: antara keberanian moral dan kalkulasi strategis. Lonjakan harga gas pada 2022 pasca-invasi Rusia memperlihatkan betapa rapuhnya ketahanan energi Eropa. Meski demikian, peningkatan pangsa energi terbarukan menunjukkan bahwa perubahan nyata sedang berlangsung. Benua ini menimbang antara stabilitas jangka pendek dan daya saing jangka panjang.
Semua ini bermuara pada satu gagasan kunci: otonomi strategis. Selama Amerika Serikat tetap menjadi penopang utama keamanan—dengan anggaran pertahanan terbesar di dunia dan dukungan militer signifikan bagi Ukraina—Eropa akan terus bercermin pada ketergantungannya sendiri. Namun dorongan untuk mandiri bukanlah upaya menjauh dari Amerika. Ia adalah usaha mendefinisikan kembali peran Eropa di dunia yang terfragmentasi—sebuah upaya memadukan ambisi normatif dengan kapasitas keras yang menopangnya.
Pada akhirnya, perdebatan di Munich bukan sekadar tentang aliansi dan anggaran. Ia menyentuh kesetiaan pada tanggung jawab historis Barat sejak 1945. Kemitraan transatlantik yang diperteguh melalui NATO telah menjadi jangkar stabilitas bagi demokrasi dan kesejahteraan. Barat membangun legitimasi bukan hanya lewat kekuatan militer, tetapi juga melalui norma, institusi, dan supremasi hukum.
Karena itu, jawaban atas pergulatan ini bukanlah pemisahan, melainkan pembaruan komitmen. Supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, dan kebebasan individu bukan sekadar retorika moral—ia adalah fondasi konkret kemakmuran yang menjadikan Amerika dan Eropa hampir separuh ekonomi dunia. Jika Barat ingin tetap relevan di tengah fragmentasi global, ia harus menautkan kembali idealisme dengan kapasitas, solidaritas dengan tanggung jawab.
Kemitraan transatlantik di abad ke-21 bukanlah hubungan ketergantungan yang pasif. Ia harus menjadi persekutuan dewasa—sadar sejarah, teguh pada nilai, dan berani menata masa depan dengan keyakinan yang diperbarui.