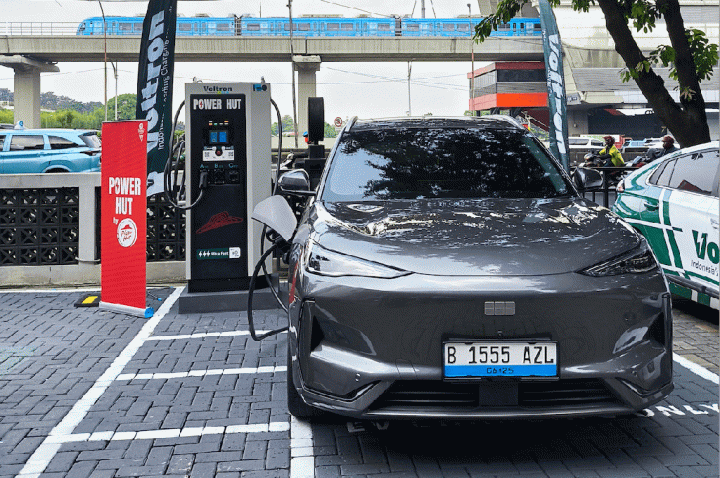Bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera telah memicu gelombang solidaritas nasional, mengisi kekosongan penanganan saat respons negara dinilai lamban dan terkendala birokrasi. Di tengah urgensi penyelamatan ratusan ribu pengungsi, inisiatif publik melalui penggalangan dana digital dan aksi sukarelawan justru hadir lebih cepat menembus wilayah terisolasi dibandingkan bantuan resmi.
Namun, niat baik ini kerap berbenturan dengan aturan izin pengumpulan uang dan barang (PUB) yang kaku, yang dikhawatirkan justru menjadi penghambat bagi warga yang ingin segera menolong sesamanya.Menghadapi situasi darurat, tata kelola donasi publik seharusnya menempatkan kemanusiaan di atas administrasi dengan melonggarkan birokrasi, di mana perizinan diposisikan sebagai laporan pasca-aksi dan bukan syarat awal yang menghambat.
Negara perlu mengubah perannya dari sekadar pengawas menjadi "pemimpin orkestra" solidaritas, memfasilitasi kedermawanan warga—yang telah terbukti sebagai modal sosial terkuat bangsa—agar bantuan dapat tersalurkan secara transparan, aman, dan tepat sasaran tanpa memadamkan semangat gotong royong.
Apa yang dapat Anda pelajari dari artikel ini?
- Mengapa penggalangan dana oleh publik menjadi krusial di tengah respons negara terhadap bencana?
- Bagaimana seharusnya birokrasi menyikapi urgensi penyaluran donasi dari masyarakat?
- Metode pengumpulan dana seperti apa yang paling efektif dan dipercaya publik saat ini?
- Apa peran ideal negara dalam ekosistem gotong royong penanganan bencana ini?
Bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera, mulai dari Aceh hingga Sumatera Barat, menyisakan duka mendalam dengan ratusan korban jiwa dan ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Di tengah situasi krisis ini, respons negara sering kali dinilai terlambat, tidak terkoordinasi, dan lamban, sehingga warga terpaksa bertahan hidup dengan mengandalkan solidaritas sesama.
Dalam kekosongan tersebut, gelombang solidaritas publik hadir sebagai penopang utama harapan para korban. Publik melihat bahwa bantuan dari perorangan, komunitas, kampus, hingga sukarelawan independen justru mampu menembus wilayah terisolasi lebih cepat dibandingkan bantuan resmi pemerintah.
Gerakan ini membuktikan bahwa energi kolektif anak muda dan masyarakat tidak apatis; mereka justru memegang peran penting dalam memastikan warga terdampak bisa selamat dan kembali bangkit. Oleh karena itu, penggalangan dana publik bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak untuk mengisi celah penanganan yang ditinggalkan oleh manajemen bencana negara yang rapuh.
Pemerintah, melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB). Aturan ini mewajibkan izin operasional bagi penggalang dana demi transparansi dan pencegahan penyelewengan.
Namun, para pakar menilai bahwa penerapan aturan yang kaku di tengah situasi darurat justru berisiko menghambat niat baik warga yang ingin menolong. Birokrasi yang rumit dikhawatirkan membuat masyarakat enggan bergerak, padahal korban bencana di Sumatera membutuhkan bantuan secepat mungkin.
Idealnya, dalam kondisi bencana yang menuntut kecepatan dan fleksibilitas, hukum harus melayani kemanusiaan, bukan justru membungkam atau memperlambatnya. Sosiolog menyarankan agar birokrasi perizinan dilonggarkan atau diubah mekanismenya dari "izin di awal" menjadi "pelaporan pasca-aksi". Dengan cara ini, bantuan dapat disalurkan terlebih dahulu untuk menyelamatkan nyawa, sementara proses administrasi dan integrasi data dilakukan setelah situasi mereda atau berjalan paralel tanpa menjadi hambatan.
Negara seharusnya tidak menempatkan dirinya sebagai "pengendali" yang membatasi empati publik, melainkan sebagai fasilitator yang mempermudah jalan bagi solidaritas warga. Jika negara hadir terlalu lambat, tugas pemerintah adalah mengejar kecepatan warga, bukan menarik rem solidaritas dengan aturan administratif yang kaku. Memotong birokrasi yang memperlambat adalah langkah konkret keberpihakan kepada korban yang sedang menderita.
Di tengah krisis kepercayaan terhadap transparansi dan kecepatan negara, publik cenderung memilih saluran donasi yang dikelola oleh figur publik, komunitas, atau platform digital yang transparan. Peran pemengaruh (influencer) dan platform penggalangan dana daring (crowdfunding) beberapa kali terbukti sangat masif dan efektif dalam memobilisasi bantuan dalam waktu singkat.
Selain penggalangan dana digital, kolaborasi lintas sektor juga menjadi metode yang sangat membantu, seperti program pengiriman bantuan gratis yang diinisiasi oleh perusahaan logistik untuk meringankan beban distribusi ke wilayah terdampak di Aceh dan Sumatera Utara. Keterlibatan sivitas akademika dan mahasiswa yang turun langsung ke lapangan juga menjadi metode efektif karena bantuan tidak hanya berupa uang, tetapi juga tenaga ahli untuk pemulihan fisik dan psikososial korban.
Efektivitas metode ini didorong oleh modal sosial bangsa Indonesia yang dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Tingginya partisipasi dalam donasi uang dan kegiatan sukarelawan menunjukkan bahwa masyarakat lebih percaya dan nyaman menyalurkan bantuan melalui kanal-kanal independen yang mampu memberikan laporan cepat dan dampak nyata di lapangan. Kepercayaan ini adalah kunci; warga ingin memastikan bantuan mereka benar-benar sampai ke tangan korban tanpa terpotong birokrasi atau dipolitisasi.
Negara harus mengubah paradigmanya dari sekadar regulator menjadi "pemimpin orkestra" solidaritas sosial. Artinya, pemerintah bertugas mengintegrasikan berbagai inisiatif warga yang tersebar agar tidak tumpang tindih dan tepat sasaran, tanpa mematikan inisiatif itu sendiri.
Pemerintah bisa menyediakan platform pelaporan satu pintu yang sederhana dan digital. Hal ini mempermudah semua pihak untuk melaporkan aktivitas donasi mereka secara transparan tanpa rasa takut dikriminalisasi karena masalah izin.
Selain itu, negara harus secara terbuka mengakui bahwa solidaritas warga adalah mitra strategis, bukan ancaman bagi kewibawaan pemerintah. Komunikasi publik yang dibangun oleh pejabat negara haruslah bernada apresiasi dan empati, bukan justru membanding-bandingkan jumlah bantuan negara dengan donasi warga yang dapat melukai perasaan publik. Komunikasi krisis harus merangkul semua pihak untuk bekerja sama menenangkan korban, bukan menciptakan persaingan.
Negara yang kuat bukan hanya dinilai dari pertumbuhan ekonominya, tetapi dari seberapa cepat ia mampu berdiri bersama warganya saat bencana melanda. Jika negara belum mampu hadir paling awal, setidaknya negara harus menjamin keamanan dan kemudahan bagi warganya yang rela berkorban waktu, tenaga, dan harta demi menyelamatkan sesama anak bangsa. Sinergi antara fasilitas negara dan ketulusan relawan adalah kunci untuk memulihkan duka Sumatera.

/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fimages%2F2025%2F12%2F09%2F09cc8c20672538af7c6b992733e754b1-010.jpeg)