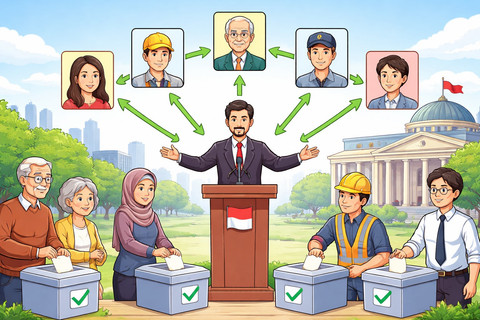Di tengah kebisingan konflik budaya yang kian mendominasi ruang publik, Minority Rule mengingatkan bahwa pertarungan simbolik sering kali menutupi relasi kekuasaan yang sesungguhnya.
Ash Sarkar, sang penulis, menunjukkan cara kerja politik identitas yang terlepas dari analisis kelas justru berisiko melemahkan solidaritas dan menguntungkan minoritas ekonomi yang menguasai sumber daya.
Buku ini menegaskan kembali, tanpa pembacaan material atas kekuasaan, politik progresif mudah terjebak dalam konflik moral yang ramai tetapi miskin daya ubah.
Perdebatan politik di berbagai belahan dunia dalam satu dekade terakhir kerap bergerak di seputar isu-isu identitas. Media sosial dipenuhi perbincangan tentang ras, jender, agama, orientasi seksual, bahasa, dan simbol-simbol budaya yang memicu kemarahan publik.
Dalam banyak kasus, konflik ini tampak begitu intens hingga seolah menjadi pusat seluruh kehidupan politik kontemporer.
Dalam keseharian, perbedaan pandangan tersebut tidak jarang merembes ke ruang privat. Percakapan keluarga, pertemanan, hingga lingkungan kerja sering kali terjebak dalam ketegangan yang berangkat dari persoalan simbolik.
Pilihan kata, sikap di media sosial, atau afiliasi politik tertentu dapat dengan cepat menggunakan label, baik sebagai progresif maupun reaksioner.
Fenomena ini diperkuat oleh arsitektur media digital yang mendorong polarisasi. Algoritma bekerja mempertemukan individu dengan pandangan yang sejalan, sembari memperbesar konflik dengan pihak yang berbeda.
Dalam situasi seperti ini, politik tidak lagi dipahami sebagai ruang deliberasi kepentingan bersama, tetapi arena pertarungan moral yang nyaris tanpa kompromi.
Di tengah kebisingan konflik budaya tersebut, pertanyaan mendasar sering kali luput diajukan. Siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh pertarungan simbolik ini?
Apakah konflik identitas yang tampak begitu dominan benar-benar mencerminkan sumber kekuasaan dan ketimpangan dalam masyarakat atau justru menutupi persoalan yang lebih struktural?
Pertanyaan inilah yang menjadi pintu masuk buku Minority Rule: Adventures in the Culture War karya Ash Sarkar. Buku ini terbit pada 2025 melalui Bloomsbury dan segera menarik perhatian karena keberaniannya mengkritik lanskap politik progresif kontemporer dari dalam tradisi kiri itu sendiri.
Ash Sarkar dikenal sebagai jurnalis, komentator politik, sekaligus aktivis kiri di Inggris. Dalam Minority Rule, Sarkar berusaha membongkar asumsi yang selama ini diterima begitu saja dalam perdebatan publik, khususnya anggapan bahwa politik hari ini didominasi oleh tuntutan kelompok minoritas sosial yang dianggap menggeser kepentingan mayoritas.
Istilah minority rule yang dipilih Sarkar bersifat provokatif. Ia tidak merujuk pada dominasi kelompok minoritas berdasarkan identitas, tetapi pada fakta bahwa kekuasaan ekonomi dan politik tetap berada di tangan segelintir elite.
Minoritas inilah yang, menurut Sarkar, sesungguhnya mengatur arah kebijakan dan distribusi sumber daya, sementara konflik identitas berfungsi sebagai pengalih perhatian.
Dalam buku ini, Sarkar menempatkan culture war sebagai medan utama analisis. Konflik budaya dipahami bukan sekadar perbedaan nilai yang muncul secara alamiah, melainkan sebagai produk politik yang diproduksi, dipelihara, dan diperluas oleh media, politisi, dan aktor ekonomi.
Perang budaya menjadi narasi yang efektif karena mampu membangkitkan emosi, ketakutan, dan kemarahan, sekaligus mengaburkan relasi kekuasaan yang lebih mendasar.
Sarkar menelusuri proses bergulirnya isu-isu seperti imigrasi, transjender, kebebasan berekspresi, dan nasionalisme kerap diposisikan sebagai ancaman eksistensial.
Isu-isu tersebut dipertukarkan dalam bahasa moral yang keras sehingga mendorong publik untuk memilih kubu, bukan untuk memahami struktur persoalan yang melatarbelakanginya.
Salah satu bagian paling penting dalam Minority Rule adalah kritik Sarkar terhadap praktik politik identitas yang berkembang di kalangan progresif liberal.
Sarkar tidak menolak keberadaan identitas atau pengalaman penindasan berbasis ras, jender, dan orientasi seksual. Namun, ia mempertanyakan cara identitas tersebut dipolitisasi.
Menurut Sarkar, politik identitas sering kali bergerak pada asumsi bahwa pengalaman hidup individu atau kelompok tertentu bersifat absolut dan tidak dapat digugat.
Lived experience dijadikan otoritas tertinggi dalam perdebatan sehingga diskusi politik berubah menjadi kompetisi klaim moral. Dalam situasi ini, perbedaan pandangan mudah dianggap sebagai bentuk penyangkalan atau bahkan kekerasan simbolik.
Masalahnya, pendekatan semacam ini berpotensi memecah solidaritas politik. Ketika identitas diperlakukan sebagai kategori yang sepenuhnya terpisah dan tidak dapat dijembatani, politik kehilangan basis kolektifnya. Alih-alih membangun aliansi luas, politik progresif justru terfragmentasi ke dalam kepentingan-kepentingan partikular.
Sarkar menilai bahwa fragmentasi ini secara tidak langsung menguntungkan elite ekonomi dan politik. Ketika kelompok-kelompok sosial saling berhadapan dalam konflik simbolik, perhatian terhadap isu upah, perumahan, layanan kesehatan, dan ketimpangan struktural menjadi kabur. Politik identitas yang terlepas dari analisis kelas berisiko kehilangan daya transformasinya.
Berangkat dari kritik tersebut, Sarkar mengajak pembaca untuk kembali melihat politik kelas sebagai kerangka analisis utama. Politik kelas dalam buku ini tidak dimaknai secara sempit sebagai konflik antara buruh dan pemilik modal semata, tetapi sebagai relasi material yang membentuk pengalaman hidup mayoritas masyarakat.
Sarkar menunjukkan bahwa krisis ekonomi global, stagnasi upah, dan meningkatnya ketidakpastian kerja merupakan pengalaman bersama yang melintasi batas identitas. Namun, pengalaman ini sering kali tidak diterjemahkan menjadi agenda politik kolektif karena tertutup oleh narasi konflik budaya.
Dalam konteks ini, culture war berfungsi sebagai mekanisme ideologis. Ia mengalihkan kemarahan publik dari struktur ekonomi menuju sasaran simbolik yang lebih mudah dipersonalisasi. Migran, minoritas seksual, atau kelompok budaya tertentu dijadikan kambing hitam, sementara struktur distribusi kekayaan tetap tidak tersentuh.
Sarkar menegaskan bahwa mengembalikan fokus pada politik kelas bukan berarti meniadakan perjuangan identitas. Sebaliknya, politik kelas dipahami sebagai fondasi material yang memungkinkan solidaritas lintas identitas. Tanpa basis material ini, politik progresif berisiko terjebak dalam moralitas tanpa kekuatan politik nyata.
Buku ini juga menaruh perhatian besar pada peran media dalam membentuk konflik budaya. Sarkar menunjukkan cara kerja media arus utama dan media digital memproduksi kepanikan moral melalui seleksi isu dan framing yang sensasional. Konflik identitas dijual sebagai komoditas karena mampu menarik perhatian dan meningkatkan keterlibatan audiens.
Dalam logika ekonomi media sosial, kemarahan (rage) dan ketakutan (fear) memiliki nilai jual tinggi. Algoritma media sosial memperkuat kecenderungan ini dengan mempromosikan konten yang memicu reaksi emosional. Akibatnya, ruang publik dipenuhi perdebatan yang dangkal dan terpolarisasi.
Sarkar melihat bahwa dalam kondisi ini, politik kehilangan dimensi deliberatifnya. Diskusi kebijakan digantikan oleh perang narasi, sementara elite politik dan ekonomi tetap dapat beroperasi relatif tanpa gangguan. Dengan kata lain, konflik budaya berfungsi sebagai selubung ideologis bagi keberlanjutan ketimpangan struktural.
Kendati Minority Rule menawarkan kritik tajam terhadap politik identitas dan perannya dalam fragmentasi solidaritas kiri, sejumlah pengulas menilai buku ini tidak sepenuhnya bebas dari problem internalnya sendiri.
Dalam ulasan di The Guardian, misalnya, buku Sarkar dipuji karena gaya bahasa yang lincah dan bernada tajam, tetapi juga dianggap tidak memberikan jawaban definitif tentang kelompok gerakan kiri dapat membangun aliansi politik yang kuat di luar kritik terhadap identitas politik liberal.
Selain itu, kritik lain menyatakan bahwa asumsi implisit dalam buku, yakni bahwa aliansi antara kelompok minoritas sosial dan kelas pekerja merupakan kondisi ”alami” atau tanpa konflik internal yang kompleks, mungkin tampak terlalu idealis.
Beberapa pengulas menunjukkan bahwa kelompok minoritas sosial dengan latar belakang sejarah dan pengalaman sosial yang berbeda tidak selalu berposisi dalam kesatuan kepentingan yang sama, dan ini menyulitkan pembentukan blok politik yang kohesif.
Kritik ini akhirnya tertuju pada diskursus, ”Sejauh mana analisis tentang fragmentasi politik kiri perlu memperhitungkan faktor historis, kultural, dan psikologis yang tidak hanya bersifat ekonomi semata?”
Ketegangan antara kebutuhan solidaritas kelas dan tuntutan keadilan identitas menunjukkan bahwa analisis struktural yang terlalu monolitik dapat mengabaikan kompleksitas praksis kehidupan politik sehari-hari.
Terlepas dari kritik tersebut, Minority Rule tetap relevan sebagai dorongan untuk menempatkan kembali analisis kelas di tengah narasi politik yang makin terpolarisasi oleh konflik simbolik.
Sarkar mengajak pembaca untuk menyadari bahwa pengalaman material, yang mencakup ketidaksetaraan ekonomi, hubungan kerja yang timpang, dan dinamika kekuasaan yang tak terlihat di balik layar, adalah landasan yang lebih kuat untuk membangun solidaritas politik yang luas.
Buku ini mengingatkan kita bahwa perbedaan identitas sosial tidak seharusnya dipandang sebagai penyebab utama perpecahan politik. Sebaliknya, perbedaan tersebut memiliki potensi menjadi titik temu ketika diartikulasikan dalam kerangka perjuangan bersama terhadap struktur yang lebih besar, yaitu kekuasaan kapitalis yang mengekstraksi nilai dari kehidupan banyak orang.
Pada akhirnya, Minority Rule bukan sekadar kritik terhadap lunturnya kelas sebagai kategori politik utama, melainkan juga ajakan untuk merefleksikan kembali konflik budaya membentuk pengalaman politik masa kini.
Buku ini tidak menawarkan resep instan, tetapi menyediakan alat konsep yang tajam untuk membaca kembali fenomena politik identitas sebagai arena yang diproduksi secara ideologis dan ekonomis. (LITBANG KOMPAS)
Serial Artikel
Resensi: Belajar Mendengar Suara yang Dibungkam
Isu kekerasan bukan hanya urusan keluarga atau pribadi, melainkan juga persoalan sosial yang memerlukan kesadaran dan tanggung jawab bersama.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F04%2F09%2Fe81b59fc-e4a5-498c-a173-6375e7ead986_jpg.jpg)