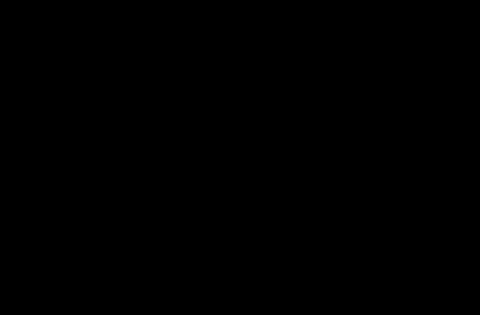Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap berbagai institusi negara, masyarakat sering kali kesulitan menemukan bahasa yang tepat untuk menyampaikan perasaan mereka. Kekecewaan, kecemasan, dan harapan yang tidak terpenuhi kerap berhenti sebagai gumaman di ruang privat atau amarah singkat di media sosial. Dalam situasi seperti ini, puisi hadir bukan sekadar sebagai karya estetis, melainkan sebagai arsip emosi sosial yang merekam perasaan kolektif suatu zaman.
Puisi memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki bahasa politik atau hukum. Ia tidak menuntut ketepatan data atau struktur argumentasi yang kaku. Puisi bekerja melalui rasa, imaji, dan pengalaman batin. Ketika masyarakat merasa tidak didengar, puisi menjadi cara untuk tetap berbicara tanpa harus berhadapan langsung dengan bahasa kekuasaan yang sering terasa jauh dan dingin.
Krisis kepercayaan publik tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari akumulasi janji yang tidak sepenuhnya terwujud, kebijakan yang terasa tidak berpihak, serta jarak yang semakin lebar antara negara dan warga. Dalam kondisi seperti ini, puisi sering lahir dari pengalaman sehari-hari: antrean panjang, harga kebutuhan yang naik, rasa takut akan masa depan, hingga lelahnya menunggu perubahan. Semua itu mungkin terlihat sederhana, tetapi justru di sanalah puisi menemukan kekuatannya.
Berbeda dengan slogan atau teriakan protes, puisi tidak selalu lantang. Ia bisa hadir dalam nada lirih, bahkan sunyi. Namun, justru kesunyian itu yang membuatnya bertahan lebih lama. Puisi menyimpan emosi yang mungkin tidak sempat terucap secara langsung. Ia menjadi pengingat bahwa di balik angka statistik dan pernyataan resmi, ada manusia dengan rasa yang rapuh dan harapan yang terus diuji.
Dalam tradisi sastra Indonesia, puisi kerap muncul di saat-saat genting. Ia menjadi ruang alternatif ketika saluran komunikasi formal terasa buntu. Puisi tidak bertujuan menggantikan kritik politik atau gerakan sosial, tetapi melengkapinya. Ia mengisi celah yang tidak bisa dijangkau oleh bahasa rasional semata, yaitu ranah perasaan dan pengalaman batin masyarakat.
Di era digital, puisi juga menemukan bentuk baru. Ia beredar cepat melalui media sosial, dibaca secara singkat, tetapi sering kali meninggalkan kesan mendalam. Potongan larik puisi mampu merangkum kekecewaan yang panjang dalam beberapa baris sederhana. Dalam konteks ini, puisi berfungsi sebagai penanda zaman, mencatat suasana batin publik yang mudah hilang di tengah arus informasi yang deras.
Pada akhirnya, puisi sebagai arsip emosi sosial mengingatkan kita bahwa krisis kepercayaan publik bukan hanya soal kebijakan atau sistem, tetapi juga soal rasa. Selama rasa itu masih ada dan terus diolah menjadi kata, masyarakat belum sepenuhnya kehilangan harapan. Puisi menjadi bukti bahwa di tengah kekecewaan, masih ada upaya untuk memahami, mengingat, dan menjaga nurani bersama.
Puisi juga bekerja sebagai ruang aman bagi emosi yang sulit disalurkan secara terbuka. Tidak semua orang memiliki keberanian atau kesempatan untuk menyuarakan kritik secara langsung. Ada rasa takut, lelah, atau sekadar keinginan untuk bertahan hidup tanpa konflik. Dalam kondisi seperti itu, puisi menjadi tempat bersembunyi sekaligus berbicara. Ia memungkinkan seseorang menumpahkan kegelisahan tanpa harus menyebut nama, institusi, atau peristiwa secara eksplisit. Justru melalui metafora dan simbol, pesan sering kali terasa lebih tajam dan bertahan lebih lama.
Keistimewaan puisi terletak pada kemampuannya menampung kontradiksi. Di dalam satu larik, harapan dan keputusasaan bisa hadir bersamaan. Puisi tidak memaksa emosi untuk rapi atau selesai. Ia membiarkan rasa ambigu tetap hidup. Hal ini penting dalam konteks krisis kepercayaan publik, karena kenyataannya masyarakat jarang berada pada posisi hitam atau putih. Banyak orang yang kecewa pada negara, tetapi masih berharap. Marah, tetapi tetap peduli. Muak, tetapi belum sepenuhnya menyerah. Puisi memberi ruang bagi kerumitan perasaan semacam ini.
Dalam kehidupan sehari-hari, emosi kolektif sering terfragmentasi. Satu orang menyimpan kecewa dalam diam, yang lain meluapkannya di media sosial, sementara sebagian memilih tidak berbicara sama sekali. Puisi mengikat fragmen-fragmen itu menjadi pengalaman bersama. Ketika seseorang membaca puisi dan merasa dirinya terwakili, di situlah terbentuk rasa kebersamaan yang sunyi. Tidak perlu saling mengenal, cukup saling memahami melalui kata.
Puisi juga memiliki kemampuan untuk melampaui waktu. Berita cepat usang, opini cepat tergantikan, tetapi puisi kerap bertahan sebagai ingatan. Larik-lariknya bisa dibaca ulang bertahun-tahun kemudian dan tetap terasa relevan. Dalam konteks krisis kepercayaan publik, hal ini menjadi penting karena rasa kecewa dan harap tidak selalu selesai dalam satu periode pemerintahan atau satu kebijakan. Puisi menjadi semacam kapsul waktu yang menyimpan suasana batin masyarakat pada satu fase sejarah.
Menariknya, banyak puisi yang lahir dari krisis justru tidak menyebut krisis itu secara gamblang. Ia berbicara tentang hujan yang tak kunjung reda, tentang jalan yang terasa semakin jauh, atau tentang rumah yang kehilangan cahaya. Simbol-simbol sederhana ini memungkinkan puisi dibaca lintas konteks. Ia tidak terikat pada satu peristiwa, tetapi pada rasa yang berulang dalam kehidupan sosial.
Di sinilah puisi berbeda dari bahasa kritik formal. Kritik politik menuntut kejelasan sasaran, sementara puisi membuka ruang tafsir. Kritik ingin perubahan segera, puisi bekerja lebih pelan. Namun keduanya saling melengkapi. Tanpa puisi, kritik bisa kehilangan sisi kemanusiaannya. Tanpa kritik, puisi berisiko terjebak dalam kesedihan yang pasif. Keduanya dibutuhkan agar masyarakat tidak hanya marah, tetapi juga memahami mengapa kemarahan itu muncul.
Di tengah krisis kepercayaan, puisi juga berfungsi sebagai cara menjaga nurani publik. Ia mengingatkan bahwa kebijakan berdampak pada kehidupan nyata, pada tubuh, pikiran, dan perasaan manusia. Puisi menolak melihat warga sebagai angka atau statistik. Ia memulihkan wajah manusia yang sering hilang dalam wacana besar tentang pembangunan, stabilitas, dan pertumbuhan.
Lebih jauh lagi, puisi dapat menjadi latihan empati. Pembaca yang mungkin tidak terdampak langsung oleh kebijakan tertentu tetap bisa merasakan getaran emosinya melalui kata. Dengan cara ini, puisi memperluas lingkar kepedulian sosial. Ia tidak memaksa pembaca untuk setuju, tetapi mengajak untuk merasakan. Dan sering kali, perubahan sikap berawal dari rasa, bukan dari argumen.
Pada akhirnya, keberadaan puisi di tengah krisis kepercayaan publik menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya kehilangan suara. Meski tidak selalu terdengar keras, suara itu tetap hidup dalam kata-kata yang dirangkai dengan jujur. Puisi menjadi bukti bahwa di balik kelelahan dan kekecewaan, masih ada upaya untuk memahami keadaan, menyimpan ingatan, dan menjaga harapan agar tidak sepenuhnya padam.
Selama masih ada orang yang menulis dan membaca puisi, krisis kepercayaan publik tidak hanya akan dicatat sebagai masalah sistem, tetapi juga sebagai pengalaman manusia. Dan mungkin, dari pengalaman itulah, lahir kesadaran baru tentang pentingnya mendengar, bukan hanya berbicara.
Dalam konteks ini, puisi juga dapat dibaca sebagai bentuk perlawanan yang halus. Ia tidak selalu hadir dengan sikap konfrontatif, tetapi justru mengganggu dengan cara yang tenang. Puisi menolak lupa. Ia mencatat apa yang ingin dilewati begitu saja oleh waktu dan kekuasaan. Ketika wacana resmi berusaha menutup kegagalan dengan narasi keberhasilan, puisi hadir sebagai catatan pinggir yang mengingatkan bahwa tidak semua hal selesai hanya karena telah diumumkan atau disahkan. Di situlah puisi berfungsi sebagai arsip alternatif, bukan arsip institusional, melainkan arsip batin masyarakat.
Puisi juga tidak tunduk pada siklus berita. Ia tidak mengejar viralitas atau relevansi sesaat. Bahkan ketika beredar di media sosial, puisi bekerja dengan cara yang berbeda. Ia mungkin dibaca sekilas, disimpan, lalu dibaca ulang di waktu lain, ketika pembaca berada dalam kondisi batin yang serupa. Dengan demikian, puisi membangun relasi personal yang tidak bisa dicapai oleh bahasa propaganda atau kampanye. Ia tidak meminta persetujuan, hanya menawarkan kejujuran rasa.
Dalam situasi krisis kepercayaan publik, bahasa sering kali kehilangan daya. Kata-kata resmi terasa kosong karena terlalu sering diulang tanpa perubahan nyata. Di titik inilah puisi justru menemukan relevansinya. Ia mengolah bahasa yang retak menjadi sesuatu yang bermakna. Puisi tidak berusaha menutupi luka, tetapi mengakuinya. Pengakuan ini penting, karena kepercayaan tidak bisa dibangun di atas penyangkalan. Ia hanya bisa tumbuh ketika rasa diakui, meski belum sepenuhnya diselesaikan.
Puisi juga mengajarkan kesabaran dalam memahami krisis. Ia tidak menawarkan solusi instan atau kesimpulan cepat. Puisi mengajak pembaca berhenti sejenak, membaca perlahan, dan merasakan. Dalam dunia yang serba cepat dan reaktif, sikap ini menjadi semakin langka. Padahal, krisis kepercayaan publik sering kali diperparah oleh respons yang tergesa-gesa, saling menyalahkan, dan kegagalan mendengarkan. Puisi, dengan ritmenya yang pelan, menjadi latihan untuk kembali memberi waktu pada rasa.
Lebih jauh lagi, puisi dapat menjadi jembatan antargenerasi. Emosi sosial yang direkam dalam puisi hari ini bisa dibaca oleh generasi berikutnya sebagai jejak sejarah batin. Mereka mungkin tidak mengalami langsung krisis yang sama, tetapi melalui puisi, mereka dapat memahami suasana perasaan yang pernah ada. Dengan cara ini, puisi berkontribusi pada ingatan kolektif yang lebih manusiawi, bukan hanya deretan peristiwa dan tanggal, tetapi juga getaran emosi yang menyertainya.
Dalam masyarakat yang semakin terpolarisasi, puisi juga berpotensi menjadi ruang temu. Ia tidak berdiri di satu kubu secara eksplisit, tetapi berbicara dari pengalaman manusia yang universal. Rasa takut, kehilangan, marah, dan berharap adalah emosi yang melintasi batas politik dan ideologi. Puisi mengingatkan bahwa di balik perbedaan posisi, ada kerentanan yang sama. Kesadaran ini penting untuk merawat kemungkinan dialog di tengah ketidakpercayaan yang meluas.
Namun, tentu saja, puisi bukan obat mujarab. Ia tidak serta-merta mengembalikan kepercayaan publik atau menyelesaikan krisis struktural. Tetapi puisi menjaga sesuatu yang sering luput diperhatikan, yaitu kepekaan. Tanpa kepekaan, perubahan apa pun berisiko menjadi mekanis dan jauh dari kebutuhan nyata masyarakat. Puisi menjaga agar rasa tidak sepenuhnya mati di tengah rutinitas dan kebisingan.
Dengan demikian, melihat puisi sebagai arsip emosi sosial berarti mengakui perannya dalam kehidupan publik, bukan hanya sebagai hiburan atau ekspresi personal. Puisi adalah cara masyarakat merekam dirinya sendiri ketika bahasa resmi gagal menampung kompleksitas rasa. Ia menyimpan apa yang tidak tercatat, mengingatkan apa yang nyaris dilupakan, dan memberi ruang bagi emosi yang tidak mendapat tempat di forum formal.
Pada akhirnya, krisis kepercayaan publik tidak hanya menuntut reformasi kebijakan, tetapi juga pemulihan hubungan antara negara dan warganya. Hubungan ini tidak semata-mata dibangun melalui regulasi, melainkan juga melalui kemampuan untuk saling memahami. Di sinilah puisi berkontribusi, bukan sebagai solusi teknis, tetapi sebagai pengingat bahwa kepercayaan berakar pada pengakuan atas rasa manusia.
Selama puisi masih ditulis dan dibaca, masyarakat masih berusaha merawat kepekaan itu. Dan selama kepekaan masih hidup, harapan untuk membangun kembali kepercayaan, meski perlahan dan penuh luka, tetap terbuka. Puisi menjadi tanda bahwa di tengah krisis, manusia masih ingin mendengar dan didengar, bukan hanya sebagai warga negara, tetapi sebagai sesama manusia.
Muhamad Robbani, Sastra Indonesia, Universitas Pamulang