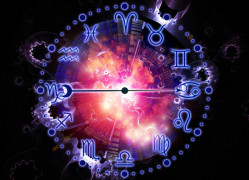Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani, menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang kembali mendekati Rp17.000 per dolar AS karena dinilai menekan industri. Hal itu mengingat sekitar 70% bahan baku produksi nasional masih bergantung pada impor.
Shinta menilai tekanan kurs yang berlangsung sejak kuartal IV-2025 dan semakin tajam pada Januari 2026 telah memberi dampak langsung terhadap sektor riil, terutama industri yang masih bergantung pada impor.
Menurut dia, depresiasi rupiah mendorong kenaikan biaya produksi melalui meningkatnya harga bahan baku, mesin dan suku cadang, energi, hingga material pendukung lainnya yang sebagian besar masih berasal dari luar negeri.
“Perlu dipahami bahwa sekitar 70% bahan baku industri nasional masih berasal dari impor. Di sektor tertentu seperti tekstil dan produk tekstil, porsi bahan baku bahkan mencapai sekitar 55 persen dari total struktur biaya produksi,” ujar Shintia dalam keterangannya, Kamis (22/1).
Nilai tukar rupiah tercatat melemah 0,06% ke level Rp16.966 per US$ pada perdagangan Rabu (21/1) lalu. Kondisi itu disebutnya secara langsung menekan margin usaha, khususnya bagi industri yang memiliki ruang penyesuaian harga terbatas. Tekanan biaya yang meningkat juga berpotensi mendorong imported inflation, yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat dan permintaan domestik.
Di sisi lain, pelaku usaha menghadapi dilema karena ruang untuk menaikkan harga jual sangat terbatas, sementara konsumsi rumah tangga belum sepenuhnya pulih. Akibatnya, kenaikan biaya tidak selalu dapat diteruskan ke konsumen, sehingga profitabilitas dan daya saing industri domestik ikut tergerus.
Shinta menjelaskan, dampak pelemahan rupiah tidak bersifat seragam di seluruh sektor. Industri dengan ketergantungan tinggi terhadap input impor seperti tekstil, alas kaki, makanan dan minuman berbahan baku impor, serta sejumlah sektor manufaktur lainnya menjadi kelompok yang paling terdampak.
Sementara itu, sektor berbasis ekspor dengan kandungan lokal tinggi berpotensi memperoleh manfaat dari pelemahan rupiah melalui peningkatan penerimaan ekspor.
Meski demikian, Shinta mengingatkan bahwa volatilitas nilai tukar yang tinggi tetap menyulitkan perencanaan usaha, penentuan harga, hingga penyusunan kontrak jangka menengah dan panjang.
“Bagi dunia usaha, tantangan terbesar bukan semata-mata pada level nilai tukar, tetapi pada volatilitasnya,” katanya. Sebab menurutnya, fluktuasi rupiah yang tajam dan sulit diprediksi menciptakan volatility cost yang tinggi dan meningkatkan ketidakpastian usaha.
Dalam jangka pendek, dunia usaha saat ini fokus pada langkah mitigasi risiko yang realistis dan adaptif. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penyesuaian struktur biaya, peningkatan efisiensi operasional, penerapan manajemen risiko seperti natural hedging, diversifikasi sumber pasokan, pemanfaatan instrumen lindung nilai, serta negosiasi ulang kontrak impor dan logistik.
Dari sisi pembiayaan, ekspansi usaha juga dilakukan secara lebih selektif dengan mengedepankan efisiensi dan fundamental bisnis yang kuat. “Secara umum, dunia usaha mengambil sikap wait and see but prepared,” ujar Shinta.