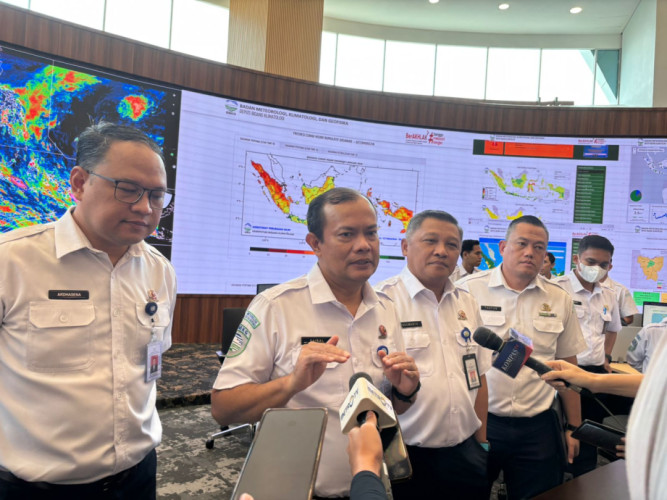Repatriasi seharusnya menjadi hak dasar pelautjalan pulang yang dijamin setelah kontrak berakhir, sakit, kecelakaan, atau kapal berhenti beroperasi. Namun dalam praktik industri pelayaran Indonesia, repatriasi kerap berubah menjadi persoalan panjang: tertunda, dipersulit, bahkan ditinggalkan. Di balik jargon perlindungan tenaga kerja maritim, repatriasi sering menjadi hak yang dinegosiasikan, bukan dijamin.
Padahal, Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) menempatkan repatriasi sebagai kewajiban mutlak perusahaan dan negara. Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016. Namun seperti banyak aspek lain dalam dunia pelayaran, kepatuhan formal belum tentu berarti perlindungan nyata.
MLC 2006, khususnya Regulasi 2.5, menyatakan bahwa pelaut berhak dipulangkan tanpa biaya apabila kontrak berakhir, pelaut sakit atau cedera, kapal karam, perusahaan bangkrut, atau kondisi kerja tidak lagi aman. Biaya repatriasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik kapal bukan pelaut, bukan agen, dan bukan keluarga.
Konvensi ini juga mewajibkan negara memastikan adanya jaminan finansial agar pelaut tetap bisa dipulangkan meski perusahaan gagal memenuhi kewajibannya. Prinsipnya jelas: tidak boleh ada pelaut yang terdampar karena persoalan bisnis.
Namun prinsip ini sering berhenti di atas kertas. Di Indonesia, kasus pelaut yang tertahan di luar negeri atau di kapal yang sudah tidak beroperasi bukan cerita langka. Repatriasi kerap tertunda dengan berbagai dalih: menunggu pengganti, menunggu jadwal kapal, menunggu “persetujuan kantor”, hingga menunggu pelaut menanggung sendiri sebagian biaya.
Dalam banyak kasus, pelaut dipaksa bertahan di kapal meski kontrak berakhir. Ada pula yang dipulangkan dengan syarat menandatangani pernyataan pelepasan hak, termasuk gaji tertunggak. Repatriasi berubah menjadi alat tawar-menawar bukan hak.
Situasi ini menunjukkan bahwa relasi kerja di industri pelayaran masih sangat timpang. Pelaut berada pada posisi lemah, sementara perusahaan memegang kendali penuh atas logistik dan administrasi.
MLC 2006 mewajibkan adanya financial security system untuk menjamin repatriasi, termasuk asuransi atau jaminan bank. Namun dalam praktik nasional, pengawasan atas jaminan ini masih minim.
Tidak semua kapal yang beroperasi benar-benar memiliki jaminan finansial aktif dan memadai. Bahkan ketika ada, pelaut sering tidak mengetahui mekanisme klaimnya. Ketika perusahaan bermasalah atau bangkrut, proses repatriasi menjadi berlarut-larut karena tidak ada skema respons cepat yang melibatkan negara.
Akibatnya, pelaut terjebak dalam ruang abu-abu hukum: haknya diakui, tetapi tidak dapat dieksekusi.
Dalam industri pelayaran Indonesia, agen perekrutan memegang peran penting. Namun posisi ini sering kali ambigu. Di satu sisi, agen mengklaim hanya sebagai perantara. Di sisi lain, pelaut kerap diarahkan untuk menyelesaikan masalah repatriasi melalui agen, bukan pemilik kapal.
Ketika terjadi sengketa, agen dan perusahaan saling melempar tanggung jawab. Pelaut berada di tengah, tanpa kepastian. MLC 2006 menegaskan bahwa tanggung jawab repatriasi tetap berada pada pemilik kapal, tetapi praktik di lapangan sering menyimpang dari prinsip ini.
Sebagai negara peratifikasi, Indonesia berkewajiban memastikan pelautnya tidak ditelantarkan. Namun intervensi negara sering bersifat reaktif baru bergerak ketika kasus viral atau mendapat sorotan media.
Mekanisme pengaduan formal belum sepenuhnya ramah bagi pelaut. Banyak pelaut tidak tahu harus melapor ke mana, atau ragu melapor karena khawatir masuk daftar hitam industri. Tanpa perlindungan terhadap pelapor, repatriasi tetap menjadi hak yang rapuh.
Repatriasi bukan sekadar tiket pulang. Ia menyangkut martabat manusia. Pelaut yang telah menghabiskan waktu berbulan-bulan di laut berhak kembali ke keluarganya dengan aman, layak, dan tanpa beban biaya.
Ketika repatriasi dipersulit, industri pelayaran sedang mengirim pesan berbahaya: bahwa pelaut bisa diperlakukan sebagai sumber daya sekali pakai. Ini bertentangan dengan semangat MLC 2006 yang menempatkan pelaut sebagai pekerja profesional dengan hak penuh.
Praktik repatriasi di industri pelayaran Indonesia menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan kekosongan hukum, melainkan lemahnya penegakan. Selama negara membiarkan repatriasi menjadi urusan negosiasi antara pelaut dan perusahaan, pelanggaran akan terus berulang.
Diperlukan pengawasan ketat atas jaminan finansial, sanksi tegas bagi perusahaan pelanggar, kejelasan peran agen, serta mekanisme pengaduan yang aman dan mudah diakses. Tanpa itu, repatriasi akan tetap menjadi perjalanan pulang yang penuh ketidakpastian bahkan sebelum kapal benar-benar berlabuh.