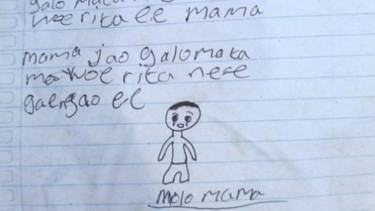Politik selalu berbicara lewat simbol—kadang lebih lantang daripada pidato. Pada penghujung Januari kemarin, Indonesia menyaksikan dua panggung yang berjalan paralel, tetapi mengirim pesan yang saling berlawanan.
Di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto sibuk merajut rekonsiliasi dengan elite oposisi, menampilkan diri sebagai pemimpin yang melampaui sekat kontestasi. Di Makassar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI)—yang kerap dipersepsikan sebagai “anak ideologis” loyalis Jokowi—menggelar Rakernas dengan kehadiran penuh Joko Widodo, namun tanpa Prabowo di kursi kehormatan.
Ketidakhadiran Presiden di acara partai pendukung utama bukan detail protokoler. Itu adalah bahasa politik. Dan dalam politik, bahasa semacam ini sering kali lebih jujur daripada narasi resmi. Sejak pelantikan, publik dibuai narasi keberlanjutan. Namun dua panggung Januari ini menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak berarti ketergantungan.
Dengan merangkul oposisi, Prabowo sedang melakukan diversifikasi kekuatan—membangun tenda politiknya sendiri, bukan sekadar berteduh di tenda lama peninggalan Jokowi.Ini kalkulasi yang rasional. Semakin luas rangkulan politiknya, semakin kecil daya tawar loyalis lama. Semakin banyak oposisi yang diajak ke meja, semakin berkurang posisi tawar mereka yang merasa “berhak” mengendalikan arah pemerintahan karena jasa masa lalu.
Dalam logika kekuasaan, Prabowo sedang bertransisi dari figur penerus menjadi pemilik panggung. Itu langkah alamiah—tetapi juga berisiko memicu friksi dengan lingkaran lama.
Narasi “Tak Diundang” dan Politik DesinisasiDalih PSI bahwa Presiden “tidak diundang karena acara internal” terdengar janggal dalam tradisi politik Indonesia. Partai pendukung utama jarang menggelar konsolidasi nasional tanpa menghadirkan kepala negara—kecuali ada kesepakatan diam-diam untuk menjaga jarak. Absennya Prabowo dapat dibaca sebagai proses desinisasi politik—pengurangan bayang-bayang Jokowi dalam simbol kenegaraan.
Prabowo tampaknya ingin menegaskan bahwa ia bukan lagi aktor subordinat dalam drama kekuasaan, melainkan sutradara baru yang punya naskah sendiri. Pesannya jelas: ia menghormati Jokowi, tetapi tidak ingin terkurung dalam warisan politik Solo.
Rakernas PSI menampilkan pemandangan yang tak lazim: Jokowi berdiri kokoh sebagai figur sentral, seolah masih menjadi pusat gravitasi politik. Sementara itu, Prabowo mengendalikan birokrasi, kebijakan, dan rekonsiliasi elite nasional dari Jakarta.
Kita menyaksikan dua pusat kekuatan yang beririsan tetapi tidak identik: Jokowi dengan jaringan relawan, pengaruh partai, dan simbol popularitas.Prabowo dengan kendali negara, legitimasi formal, dan strategi rekonsiliasi elite.
Jika hubungan mereka benar-benar harmonis tanpa ketegangan, kehadiran Prabowo di Makassar semestinya menjadi penutup yang manis. Namun pilihannya untuk tetap di Jakarta dan berdialog dengan lawan politik lama mengirim sinyal berbeda: stabilitas nasional versi Prabowo lebih penting daripada romantisme politik dengan basis lama.
Di Mana Posisi Gibran?Di tengah jarak yang mulai terbentuk, posisi Gibran Rakabuming Raka yang selama ini tak dianggap ada dan menjadi teka-teki kekuasaan. Di sini jelas posisi Gibran tak akan menjadi jembatan yang meredam friksi antara Prabowo dan Jokowi, dan justru menjadi arena tarik-menarik kepentingan dua kubu.
Gibran berada di posisi yang sebenarnya strategis tetapi rapuh: dekat dengan pusat kekuasaan, namun juga terikat kuat pada warisan politik ayahnya. Gibran penuh dengan narasi tak mampu, termasuk tak mampu memainkan peran sebagai mediator yang otonom, ia tak cukup pikir untuk menjadi aktor penyeimbang. Ia sekadar anak yang lahir dari wajah gelap konstitusi dan menjadi pajangan dari wajah Jokowi dalam panggung kekuasaan negara, dan akhirnya potensi konflik elite kubu Prabowo dan Jokowi akan terus mengeras.
Januari 2026 menandai babak baru: Prabowo mulai menulis narasinya sendiri. Hubungan Prabowo–Jokowi yang semula tampak monolitik kini memperlihatkan retakan strategis—bukan perpecahan terbuka, tetapi pergeseran gravitasi kekuasaan. Pertanyaan bagi publik bukan lagi apakah ada jarak, tetapi seberapa jauh jarak itu akan melebar. Apakah ia akan berujung pada kolaborasi profesional yang sehat, atau menjadi kompetisi pengaruh antara Istana dan Solo?
Yang pasti, politik telah membuktikan satu hal: dalam kekuasaan, tidak pernah ada ruang bagi dua matahari yang bersinar sama terangnya.